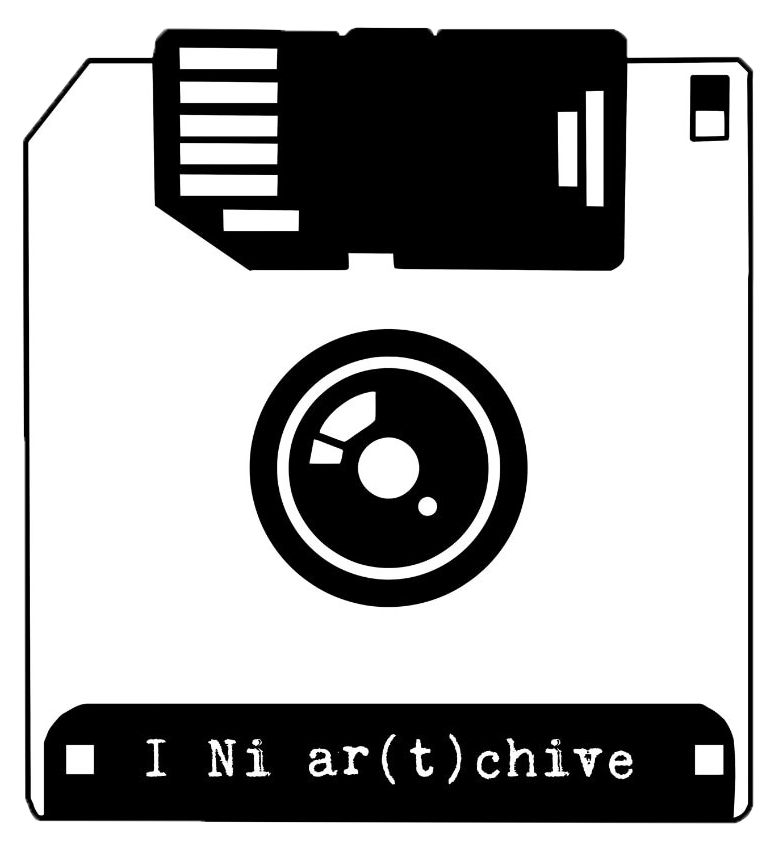Namaku Alif Syahdan. Seorang pelukis. Atau setidaknya, dulunya aku pelukis. Sekarang, aku lebih sering dianggap pengganggu. Penggerutu yang tua sebelum waktunya. Tapi jangan percaya semua kata orang. Mereka cuma takut pada orang-orang yang mengingat. Aku datang dari lubang waktu yang tertutup kabut dan kisah-kisah yang tak sempat selesai. Dan kisah ini adalah salah satunya.
Aku tiba di Payakumbuh dengan sepasang kanvas lusuh, satu gitar tua, dan kepala penuh amarah. Aku tak tahu aku mencari apa, hanya tahu aku tak bisa tinggal di kota yang terlalu rapi, terlalu bersih dari ingatan. Dan di sinilah aku bertemu mereka—anak-anak jurang.
Di kaki Bukit Barisan berdiri rumah gadang yang sudah kehilangan cat dan hormat. Dari jendela yang menganga, terdengar suara alat musik, diskusi panas, kadang tangisan, kadang ledakan tawa. Mereka menyebut tempat itu Ruang Saka. Dan penghuninya bukan keluarga adat, melainkan sekumpulan seniman muda yang keras kepala, miskin, dan nekat.
“Di sinilah seni bukan jadi pelarian,” kata seorang perempuan berkacamata yang menggambar mural dengan cat kaleng bekas. “Tapi jadi senjata.”
Namanya Raya. Wajahnya teduh, suaranya seperti serpih seruling bambu. Ia menarikan tubuhnya di antara patahan lantai dan mimpi-mimpi kolektif. Dia penyair, aktivis, penari, pencatat sejarah. Dia luka yang berdansa. Dan barangkali, ia juga nyala yang menulari kami semua.
Aku tinggal di loteng, tidur di atas papan reot dan kertas-kertas ide orang lain. Pagi-pagi, kami ngopi dengan ampasnya; malam-malam, kami menggambar dengan sisa tinta. Kadang kami lapar. Kadang kami gemetar. Tapi kami tak pernah berhenti membuat. Kami tahu kami sedang dikejar waktu.
Kami mengadakan pertunjukan teater tentang tanah ulayat yang dijual di bawah meja. Kami memamerkan potret ibu-ibu petani yang dikriminalisasi karena menolak tambang. Kami merekam lagu-lagu lama dari suku Mentawai yang hendak diganti suara mesin. Kami membacakan puisi-puisi yang tak akan dimuat koran mana pun. Di setiap pentas, selalu ada satu kursi kosong: untuk penonton yang takut datang.
Kami tahu kami sedang bermain-main di mulut api. Dan api itu benar-benar datang. Suatu malam, dinding rumah gadang dilumuri cat hitam. Sebuah mural tentang perjuangan digunting di tengah malam. Besoknya, dua orang laki-laki berjaket kulit datang, menawarkan “solusi damai”—yang berarti: bubar diam-diam.
Kami menolak. Kami bukan daun-daun tua yang siap luruh. Kami akar-akar kecil yang keras kepala. Raya berdiri di depan panggung dengan mata menyala. “Kalau kita diam, cerita kita akan ditulis oleh orang yang membenci kita.”
Beberapa minggu kemudian, Raya hilang. Begitu saja. Tak ada jejak. Hanya selendang tari yang ia tinggalkan tergantung di tiang panggung. Ada yang bilang dia kabur. Ada yang bilang dia dibawa paksa. Aku tidak percaya dua-duanya. Aku tahu dia tak pernah pergi. Ia tinggal di setiap kalimat yang kami teriakkan. Di setiap cat yang kami oleskan.
Malam-malam setelahnya aku menulis surat untuknya. Surat yang tak pernah kukirim. Surat tentang panggung yang retak, tentang potret wajahnya yang mulai pudar, tentang kabut yang tak mau pergi dari lereng bukit ini. Tapi juga tentang anak-anak baru yang datang. Anak-anak yang bahkan tak tahu siapa itu Raya, siapa itu Alif. Tapi mereka tahu satu hal: bahwa di Ruang Saka, mimpi bisa tumbuh meski akar penuh luka.
Sekarang aku duduk di jendela, memandang langit Payakumbuh yang selalu tampak muram. Tanganku tak lagi kuat untuk melukis, tapi aku masih bisa bercerita. Tentang ruang-ruang kecil yang melawan dilupakan. Tentang anak-anak jurang yang tak sudi diam. Tentang nyala yang tak padam, meski kabut terus turun dari gunung.
Di tiang utama Ruang Saka, tertulis kata-kata yang pernah diucapkan Raya:
“Jika kita tidak menuliskan sejarah kita sendiri, orang lain akan menuliskannya untuk kita—dan mereka akan lupa mencatat luka kita.”
Maka aku menulis ini, bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan: kesenian bukan milik galeri. Ia milik rakyat yang tak punya suara. Ia milik anak-anak jurang yang terus tumbuh, melawan arus, dan menulis bab baru sejarah kita.
____
Pernyataan
Cerita, tokoh, tempat, dialog, dan peristiwa yang terdapat dalam trilogi “Anak-Anak Jurang” sepenuhnya merupakan karya fiksi. Semua unsur di dalamnya lahir dari imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mewakili individu, lembaga, atau peristiwa nyata secara langsung.
Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, situasi, atau kejadian dengan kenyataan, hal tersebut adalah kebetulan semata dan bukan hasil dari niat atau maksud tertentu.
Cerita ini ditulis untuk kepentingan ekspresi sastra, refleksi sosial, dan pembacaan artistik atas ruang seni, perlawanan budaya, serta ingatan kolektif yang hidup di masyarakat. Harap dibaca dengan semangat apresiatif dan kritis sebagaimana layaknya karya fiksi.
_________
sungai | iniartchive