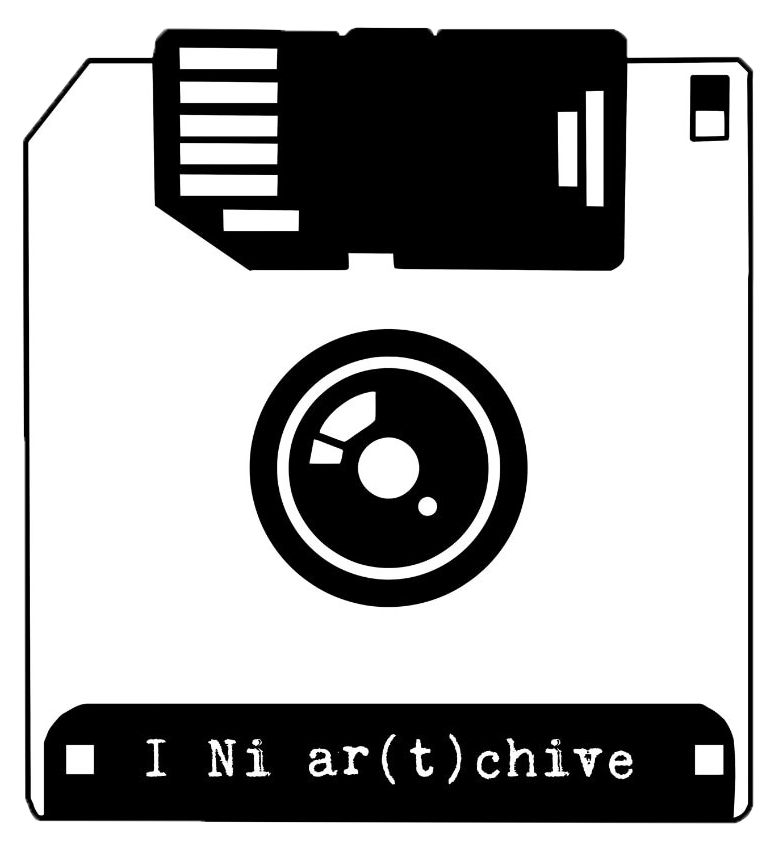“hai..hai...” Naira, bocah perempuan meneriaki Fari dan Rafi yang sedang sibuk berlarian,berkejaran.
“Ahh…” Fari bergumam, sambil tak memperdulikan Naira dan terus mengejar Rafi.
Matahari menggantung tepat di atas kepala, hamparan rumput hijau luntur, debu terbang menempel pada keringat, pada wajah hitam terbakar siang.
Sebuah botol diselipkan di sisi roda sepeda mungil, suara yang dihasilkan memicu semangat Fari untuk semakin cepat mengayuh. Sementara Rafi dan Naira kini tertawa melihat ekspresi Fari yang terus mencoba menghasilkan suara nyaring menyerupai knalpot motor bersuara nyaring, knalpot 2 tak, khas brandalan desa.
Perempuan tua duduk di sebuah bale yang diletakkan di bawah pohon juwet. Lokasi teduh yang menjajikan hembusan angin. Siapa yang kuat di dalam rumah, ketika ruangan telah menjadi sauna yang memeras keringat. Beberapa ekor sapi melintas, menghidari paparan matahari, mencari rumput yang lebih hijau, lebih berair. Dahaga lebih menyiksa dari pada lapar.
Di sebuah pondok berdiri di utara ujung halaman, menjadi sebuah posko pemantau. Semua yang melintasi padang rumput akan terlihat jelas. Pekerja pabrik dengan helm kuning, pelindung kepala dari benturan, namun sayangnya tidak cukup mampu untuk melindunngi kepala dari susupan akan kenyamanan yang disuapkan. Sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda tajam tapi tak membuat langkah lebih ringan. Seragam yang membuat mereka tampak lebih gagah, tetapi kehilangan kepekaan untuk tergugah. Pegawai pabrik yang sering melintasi padang rumput yang mereka ciptakan. Padang rumput yang kian hari kian gersang.
Pasak-pasak raksasa teronggok, tersusun di salah satu sudut tanah lapang,tersusun rapi. Sementara reruntuhan bangunan menjadi ornamen yang menghiasi padang rumput. Jejak rumah, jejak keluarga yang kalah, menyerah, kalah. Puing-puing kekelahan yang belum ditelan kekuatan tamak kemajuan jaman.
Dan bocah-bocah berlarian di antara puing, ornamen kekalahan dan rumput yang kian hari semakin pudar.
“Fari...” perempuan tua itu memanggil “taruh sepedanya!” perintahnya.
Perintah yang lahir dari kalimat, kalimat yang tak dihiraukan.
Fari semakin cepat mengayuh, semakin menjauh meninggalkan halaman, suara yang dihasilkan semakin nyaring.
“ayo cepat” suara Rafi tidak sabar, meminta Fari kian cepat mengayuh. Tidak sabar menanti giliran.
Sementara Naira hanya tertawa melihat kelakuan kakak-kakak sepupunya.
Perempuan tua itu hanya bisa melihat bocah-bocah kecil pembawa kecerian ke halaman rumah. Halaman rumah yang kian kering dan gersang.
Dia tak bisa membayangkan betapa sepi rumahnya jika tidak ada cucu-cucunya itu. Betapa sunyi rumahnya jika dia hanya hidup dengan sang suami,lelaki yang tidak kalah lelah, tidak kalah renta,tidak kalah keriput.
Lelaki tua yag telah kehilangan ketegapannya, yang hannya bisa duduk di pondok dibawah pohon asam, sambil melihat semua yang melintas dihadapannya. Sesekali menyalurkan keisengannya, menggunakan ketapel untuk membidik sapi tetangga yang coba masuk ke pekarangan, masuk untuk menikmati rumput yang tampak lebih hijau dari kejauhan.
Bocah-bocah itu masih berlarian, kini sepeda tidak lagi di bawah kendali Fari. Pedal sudah berada di bawah kaki Rafi,yang tidak kalah kencang mengayuh, memacu sepeda dengan suara nyaring hasil gesekan roda dengan botol air mineral yang disepilkan, melaju kencang menuju sisa-sisa reruntuhan.
“kak Rafi…” Naira berteriak, memberi semangat, mencari perhatian. Fari menatap sodaranya memacu sepeda. Memandang, terengah, dengan keringat dipelipis dan wajah hitam terbakar.
“sudah,berhenti dulu!” perempuan tua berteriak.
Teriakan yang tak lagi dihiraukan, tak pula cukup kuat untuk membuat ke tiga bocah itu berhenti melakukan yang mereka suka.
Suara yang keluar,seberapapun kerasnya tetap saja hanya sebuah suara perempuan tua. Seperti halnya tangan dan jemari yang telah dirayapi waktu, berkerut, keriput.
Demikian pula dengan pita suaranya. Pita suara yang kian mengendor, meleleh, membuat suaranya tak lagi bisa selirih dan lantang dahulu. Tidak lagi sekuat ketika nafas masih panjang, lengan masih kencang mengontrol jemari untuk cekatan melakukan semua pekerjaan.
Tidak lagi seperti ketika bahu masih kencang membahu, melihat semua celah mengambil kesempatan demi bisa bertahan dan menghidupi anak-anak yang lahir dari rahimnya. Menghidupi anak-anak yang kini telah memberikannya cucu-cucu.
Salah tiganya, cucu-cucu yang kini ada dihadapannya. Berkeliaran bermain dihadapannya. Berlarian di halaman dengan asik bermain, di tengah terik hingga tak lagi mendengar nasehan, arahan dan kekhawatiran yang diteriakkan.
Tiga orang bocah yang tidak pernah sempat melihat bagaimana perempuan tua yang sedang mengawasinya tersebut membesarkan orang tua mereka. Terjaga sebelum kumandang adzaan subuh, yang kemudian dalam sunyi mengumandangkan keyakinan akan harapan untuk orang tua mereka yang masih terlelap. Menghadirkan sarapan di meja makan yang siap disantap, ketika orang tua mereka baru membuka mata dan memutuskan turun dari tempat tidur.
Lalu ketika orang tua mereka pergi mengenakan seragam, menuju ruang-ruang kelas yang menertibkan, perempuan tua itupun melangkah meninggalkan rumah, menuju ladang.
Sepetak tanah yang diwarisi dari mertuanya, warisan yang didapatkan sang mertuanya dari mertua sebelumnya. Demikian sepetak tanah yang kini masih didiaminya turun, dari beberapa generasi di atas diturunkan hingga kini dan kemudian nanti ke cucu yang kini sedang berlarian di sekitar petak tanah terssebut.
Hal tersebut akan berlangsung, jika tenaga dan suaranya masih bisa terdengar sekuat keyakinan dan imannya, dan jika anak-anaknya memiliki keyakinan dan iman yang serupa.
Pada akhirnya dia hanya perempuan tua, yang semenjak kelahiran pertamanya mendedekasikan hidupnya untuk kehidupan anak dan anak-anak yang dilahirkan oleh anak-anaknya. Dan apapun yang dimilikinya pada akhirnya akan diserahkan pada anak-anaknya, kecuali luka dan duka, yang disimpan rapat. Disimpan jauh di dalam belulang yang terbungkus otot dalam kulit yang kian berkerut.
Hingga kini ketika otot-otot mengendur dan kulit meleleh, luka dan duka tetap dikuncinya rapat-rapat.
Bahkan ketika kini suaranya tak lagi cukup dihiraukan, cukup dihiraukan untuk membuat ketiga bocah itu meringkuk duduk di dipan di bawah pohon sambil menunggu terik berlalu, dia masih setia menjaga anak-anak dari anaknya, menjaga agar mereka baik-baik saja. Baik-baik saja dalam menikmati permainan yang menggembirakan mereka.
“Kak Rafi... Kak Rafi” Naira berteriak, dengan huruf r belum terucap dengan tegas.
Rafi masih asik mengayuh sepeda di atas lantai yang tersisa. Lantai yang telah ditinggalkan, lantai yang masih tampak jelas.
Sisa lantai rumah dari mereka yang dahulunya menjadi tetangga. Sisa lantai dan sisa dinding yang telah menjadi puing. Sementara bangunan lainnya telah rata dengan tanah dan menjadi lapang ditumbuhi rumput. Rafi dan Fari, 2 bocah yang masih setia bermain di area tersebut, sesekali Naira ikut menambah keceriaan dan keriangan. Naira hanya bisa bermain bersama kedua kakaknya ketika salah satu atau kedua orang tuanya datang mengunjungi neneknya. Seorang perempuan tua yang masih setia menjaga tanah,tempat dia tumbuh. Tanah yang diwariskan ke padanya. Tanah yang menjadi ruang dia merawat keluarganya.
Satu persatu tetanga merelakan warisannya. Meninggalkan tanah merelakan rumah. Ganti untung tiba bersama dengan serangkaian mimpi yang dihembuskan tentang tanah baru. Rumah baru. Mimpi yang mekar seiring nominal rupiah yang masuk dalam rekeing, dengan jumlah nol tidak sebanyak biasanya. Nominal yang hadir sebagai kompensasi atas tiap jengkal amanah, tiap inchi ingatan, dan cerita terampas.
Nominal menjanjikan tanah baru, rumah baru dan cerita baru.
Dan kaki harus diangkat, langkah harus diayun dan warisan, amanah dan segala ingatan harus ditinggalkan. Mimpi dan harapan baru harus disosngsong.
Dan di depan kerugian meyambut. Kerugian utama tentu rasa bersalah telah melepaskan amanah. Amanah dalam bentuk tanah waris yang harusnya mereka jaga untuk kemudian bisa diteruskan kepada anak-anak yang lahir setelahnya. Warisan yang dimanatkan untuk generasi yang lahir kemudia, generasi-generasi yang kemudian menjadi dahan dan batang pohon keluarga mereka.
Penyesalan pertama yang harus mereka ratapi di balik dinding-dinding rumah baru,hasil penggantian tanah dan bangunan mereka.
Penyesalan bahwasanya kini mereka harus hidup di tempat yang baru, dengan kebiasaan yang baru kemudian menyusul. Keluarga di depan rumah yang dahulu bisa diajak berbagi lelah kini sudah tak ada lagi. Berganti dengan keluarga yang belun dikenal dan tak tahu apakah mereka punya telinga yang sama, punya mulut yang sama, punya hati yang sama untuk kemudian ikut bersama-sama merasakan bagaimana hari yang dilalui begitu melelahkan.
Penyesalan yang kian menghimpit ketika mendapati rupiah yang didapat kian menipis setelah terkuras oleh apa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Terkuras oleh segala ingin yang selama ini menjadi angan yang diidam-idamkan dan membuat mereka semakin giat bekerja untuk mewujudkannya.
Bahkan ketika beberapa angan berhsil mereka wujudkan, mereka tidak lagi tahu apa yang harus dikejar dan bagaimana mengejarnya, ketekunan dan kerja keras seolah menguap setelah mimpi tak lagi menjadi mimpi. Dan bahkan ketika mimpi yang berhasil diwujudkan rasanya tak seperti dalam bayangan, sebagaimana ketika mimpi itu masih berupa sebuah impian.
Sementara kesederhanaan telah roboh tepat ketika bangunan-bangunan yang berhasil dibangun dengan ketekunan dan keuletan roboh oleh buldoser kemajuan yang dijanjikan.
“nek,ada roti?” Fari tiba-tiba bertanya pada perempuan tua yang melempar pandangannya jauh ke kompleks bangunan beratap genteng yang masih terlihat coklat.
“minta sama ibu sana” jawabnya. Tidak ada sesuatu yang bisa langsung didapat dengan sekali minta.
“aduh,fari males minta sama ibu” Fari memohon “ada ndak nek?”
“ada, ambil di toples dikamar nenek” belum lagi kalimatnya selesai Fari sudah berlari meninggalkan perempuan tua itu “ambil juga buat adik-adikmu”.
“iya” teriak Fari.
Naira hanya melihat kakak sepupunya berlari masuk ke dalam rumah. Bayangan pohon memanjang ke barat. Perempuan tua itu mengalihkan pandangannya, dilhatnya Rafi masih asik dengan sepedanya dan puing-pung rumah tetangganya.
Ada ingatan bagaimana dahulu mereka bisa saling berbagi obrolan diteras rumah itu. Berbagi cerita tentang sayur apa yang dia masak, tentang ikan yang bisa digoreng, tentang cabai dan sayur yang bisa dipetik. Tentang rumput yang paceklik, tentang biaya anak-anak sekolah yang mencekik.
Ada kekhawatiran yang melintas, sampai kapan dia akan kuat mempertahankan amanat ini, sampai kapan dia bisa menjaga keyakinannya, sampai kapan anak-anaknya akan mendengar suaranya. Bukankah kemajuan dan iming-iming hidup yang lebih baik selalu lebih manis dari apa yang sebenarnya harus ditanggung. Di tengah tubuh yang kian merenta, nama obat yang kian panjang ditulis di kertas resep, nafas yang kian sesak, suara akan menjadi semakin kecil. Apalagi jika pada kenyataannya panen dari sepetak kebun telah menghanatinya.
Kekhawatiran yang terpancar dari matanya, bertahan adalah pilihan yang berat. Bertahan menjaga amanat selalu berat, lebih berat dari pada ketika menginginkan dan akhirnya bisa menggenggam amanat tersebut.
Apalagi ketika bertahan menjaga amanah, warisan yang diwariskan dengan bersading, bertetangga sebuah cerobong raksasa yang dengan konsisten menghembuskan asap abu-abu ke angkasa.
Racun yang terus dihembuskan ke udara mengiringi deru mesin yang terus menyala. Sementara usia menua otot pernapasan kian renta, tubuh harus ditopang dengan rutin menyambangi dokter dan menebus daftar obat yang terus bertambah. Sementara kondisi tubuh terus menurun, biaya kesehatan kian naik dan harus ditanggung sendiri. Sementara keyakian harus terus ditenenun, udara terus diracuni. Dan perempuan tua itu harus tetap bertahan dalam kubangan yang kian mengering.
“Rafi” Fari memanggil adiknya dengan mulut telah berisi segigit roti. Menunjukan roti yang dia ambilkan untuk adiknya. Roti ditangan Naira juga telah menyapa bibirnya.
Rafi mengayuh sepeda menghampiri kakanya “kamu mau?” Rafi menawarkan sepedanya pada sang kakak.
“tidak. kamu aja” jawabnya pendek.
Perempuan tua itu seoalah telah kehilangan seleranya pada makanan. Bahan makanan yang dahulu bisa didapatkan dengan mudah dari kebun atau dibawa dari laut oleh suaminya kini seolah menjadi dongeng.
5 tahun kehadiran tetangganya, sebuah PLTU Batubara telah berhasl merenggut segalanya. Tanah yang subur, laut yang makmur kini hanya menjadi hikayat dalam syar-syair puitis penyair gombal.
Ladang yang bertahun-tahun menghidupi dia dan keluarganya kini telah mengering, air yang dibawa akar-akar pohon untuk mengisi sungai telah lama menghilang seiring hilangnya pohon-pohon yang dibabat untuk persiapan lahan pembangunan PLTU tahap ke-2.
Haya cekungan-cekungan kering yang ditumbuhi perdu dan lembab akibat sisa huja yang terperangkap. Kelapa yang setia menyusuinya setiap dua bulan kini telah menghianatinya, sudah 4 bulan dia harus melalui hari tanpa sebutir kelapa yang bisa dia uangkan. Laut yang dahulu selalu membiarkan anaknya memanen ikan kini lebih sering mengembalikan putranya, pulang ke rumah setelah seharian terombang-ambing dengan tangan hampa, tanpa seekor ikan pun.
Tapi amanat terus harus dijaga, keyakianan tetap harus dirawat, meski dia tahu racun juga harus terus dia dan keluarganya hirup.
“sudah kalian mandi, lalu masuk rumah” perempuan tua itu menyuruh ketiga cucunya. Menyadari semakin lama mereka berada dihalaman, semakin banyak pula racun yang dihembuskan PLTU harus mereka hisap.
Racun yang harus dihisap oleh Naira, Fari dan Rafi. Adalah racun yang sama yang harus dihisap oleh si perempuan tua. Bahkan suaminya ,anak-anaknya, anak dari anak-anaknya dan bahkan cucu dari cucu-cucunya akan menghisap racun yang sama, racun yang hadir dan menjadi tetagganya. Menjadi tetangga tanpa tanta meminta ijin, hadir memaksa dan terus dia tolak hingga hari ini.
L.Taji