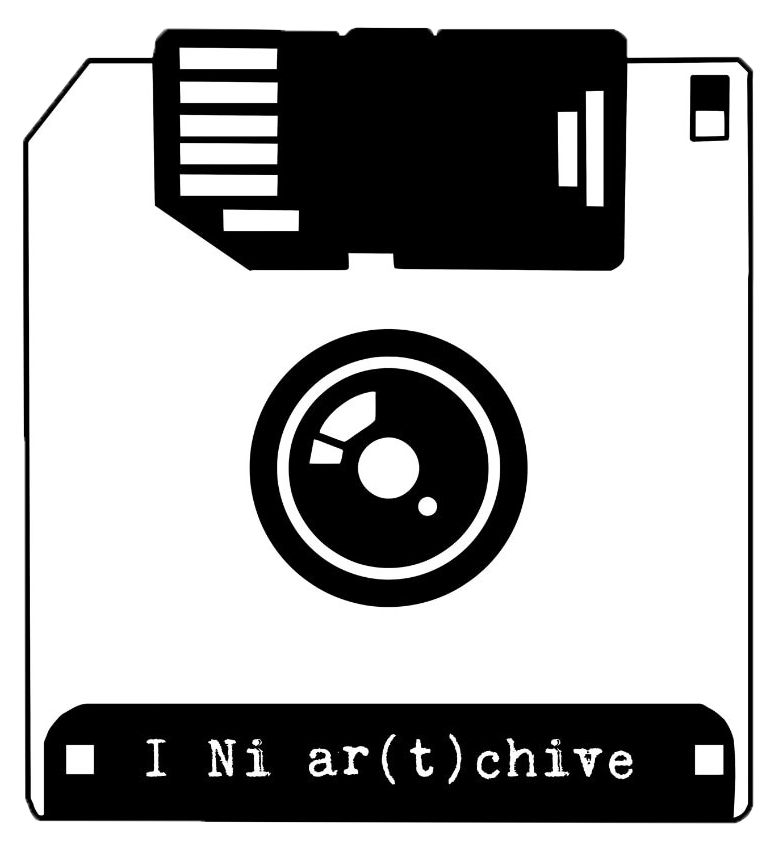Bayangkan sebuah lukisan dari abad ke-19: perempuan Jawa dengan kemben sutra, duduk di bawah pohon beringin yang rindang, dikelilingi alam tropis yang "perawan". Itulah gambaran khas Orientalisme—mata Eropa yang menjadikan Nusantara sebagai objek eksotisme, diabadikan dalam kanvas pelukis Belanda seperti Jan Toorop atau Walter Spies. Tapi di balik romantisasi itu, tersembunyi luka kolonial: narasi Timur yang ditulis oleh Barat, untuk konsumsi Barat.
Namun, pada 1857, seorang pelukis Jawa bernama Raden Saleh mengguncang dunia seni Eropa. Lewat karya "Penangkapan Pangeran Diponegoro", ia tak hanya membalikkan narasi Belanda yang menyebut Diponegoro sebagai "pemberontak", tapi juga menciptakan ikon pahlawan yang gagah berani. Saleh, yang pernah tinggal di Eropa, paham betul bahasa seni Barat. Tapi ia memilih menggunakan kuasnya untuk membangun monumen kebanggaan lokal. Karya itu bukan sekadar lukisan—ia adalah manifesto politik pertama seni rupa Indonesia.
Di era 1950-an, ketika Indonesia masih merangkak dari reruntuhan kolonial, Affandi melukis dengan jari-jarinya yang penuh cat. Petani, nelayan, dan rakyat jelata menjadi subjek utamanya. Ekspresionismenya yang liar bukan lagi tentang keindahan alam tropis, tapi tentang keringat, luka, dan semangat orang kecil. Sementara itu, Hendra Gunawan—seniman Lekra—menciptakan "Pengantin Revolusi", menggambarkan pengantin perempuan dengan pistol di tangan. Lukisan itu adalah tamparan bagi Orientalisme: perempuan Indonesia tak lagi objek pasif, tapi pejuang yang siap mempertahankan kemerdekaan.
Tapi jejak Orientalisme tak mudah dihapus. Pada 2019, lukisan Walter Spies "Balinese Landscape" terjual Rp 42 miliar di Sotheby’s Singapura. Angka fantastis itu mengungkap paradoks: pasar seni global masih terpesona oleh romantisme kolonial. Padahal, menurut Indonesia Art Market Report (2023), hanya 12% seniman Indonesia yang karyanya dihargai di atas Rp 1 miliar di lelang internasional. Seolah ada hierarki tak kasatmata: karya "Timur" yang dianggap "otentik" harus melalui filter estetika Barat.
Seniman kontemporer seperti FX Harsono menolak diam. Dalam karya "Writing in the Rain" (2011), ia duduk di tengah hujan, menulis nama Tionghoa-nya berulang kali di atas batu—sebuah kritik terhadap penghapusan identitas selama Orde Baru. Karya ini tak hanya tentang politik identitas, tapi juga menjawab Orientalisme yang kerap mengkotak-kotakkan budaya Nusantara menjadi "etnis murni". Sementara Titarubi, lewat instalasi "Shadow of the Sultan" (2017), menggunakan rantai besi dan rempah-rempah untuk mengingatkan kita: jejak kolonialisme masih melekat dalam sistem pasar seni global.
Ariel Heryanto, kritikus budaya, pernah berujar: "Orientalisme bukan sekadar sejarah, tapi virus yang masih hidup dalam galeri, kuratorial, bahkan algoritma media sosial." Pernyataan ini terasa relevan ketika melihat platform digital hari ini. Lukisan "wanita Bali bertelanjang dada" masih viral sebagai simbol eksotisme, sementara karya-karya seniman perempuan kontemporer Indonesia seperti Arahmaiani harus berjuang lebih keras untuk diakui.
Tapi ada harapan. Riset ArtAsiaPacific (2022) mencatat, 45% seniman Indonesia kontemporer memasukkan tema dekolonisasi dalam karya mereka—naik 20% sejak 2010. Mereka tak lagi hanya bereaksi terhadap Orientalisme, tapi membangun bahasa visual baru. Misalnya, kolektif seni Ruangrupa yang mengkuratori Documenta 15 (2022) dengan prinsip "lumbung", menggeser fokus dari individualisme seniman ke ekosistem gotong royong. Ini adalah tamparan halus bagi sistem seni Barat yang hierarkis.
Di tengah riuh pasar seni dan algoritma yang kadung bias, seniman Indonesia terus menulis ulang kisah mereka. Seperti kata Raden Saleh: "Seni adalah bahasa universal, tapi jangan biarkan orang lain menceritakan kisahmu dengan perspektif mereka."
"Setiap goresan, instalasi, atau performans adalah halaman baru dalam buku besar seni rupa Indonesia. Di sini, Orientalisme tak lagi jadi penjajah, tapi bahan bakar untuk membakar kreativitas. Mau menyelami lebih dalam arsip seni yang memberontak?
iniartchive