
Indira Laksmi hadir sebagai pelopor fashion Bali yang memadukan sentuhan klasik, etnik, dan kontemporer. Sejak berdiri pada tahun 2016, Indira Laksmi berkomitmen untuk menghidupkan kembali tradisi, budaya, dan adat istiadat melalui karya yang tak lekang oleh waktu. Lebih dari sekedar momen spesial, melainkan warisan yang abadi.
Dengan pandangan bahwa kecantikan sejati adalah keiklasan, Indira Laksmi terus berkarya menghadirkan busana yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyentuh jiwa.
Pada tanggal 30 Agustus 2025, Indira Laksmi menggelar pameran dengan tajuk “From Sketch To Soul” yang berlokasi di studio Indira Laksmi dan Tegal Temu Space. From Sketch To Soul adalah sebuah pameran kreatif dan pertemuan intim yang mengajak tamu untuk melihat lebih dekat perjalanan di balik setiap karya Indira Laksmi.
Pameran ini tidak hanya menampilkan hasil akhir berupa busana, tetapi juga membuka proses dibaliknya, mulai dari sketsa awal, inspirasi, hingga detail pengerjaan yang penuh makna. Melalui instalasi visual, sesi interaktif, hingga perbincangan santai bersama desainer, para tamu diajak memahami bagaimana sebuah sketsa sederhana dapat berkembang menjadi sebuah cerita visual. Lebih dari sekedar pameran, From Sketch To Soul adalah perayaan atas proses, kreativitas, dan jiwa yang tertuang dalam setiap garis, kain, dan cerita.
Pameran dimulai dengan sesi registrasi oleh pengunjung pada pukul 15.30 WITA, kemudian dilanjutkan dengan opening by MC, opening speech by Gung Ama. Setelah itu dilanjutkan dengan house tour di studio Indira Laksmi yang dimulai dari ruang depan yang dihiasi benang menjuntai dan dua manekin yang distyling dengan wardrobe Idup Panak, kemudian tamu digiring ke ruang wardrobe yang terpajang kain-kain milik Indira. Setelahnya tamu diajak menuju ruang make up, terdapat dinding yang dihiasi dengan foto-foto klien menggunakan kain dan make up Indira Laksmi. Terdapat Sketch Wall Installation yaitu showcase semua sketsa koleksi Indira Laksmi, dinding galeri berisi deretan sketsa arsip yang dibingkai. Sebagai background foto.
Setelah house tour pengunjung diarahkan untuk menuju teras Indira Laksmi, area interaktif tempat tamu dapat menambahkan coretan, catatan kecil / inspirasi mereka. Tamu diarahkan untuk mewarnai sketsa dengan cat warna bebas yang telah disediakan.
Dalam pameran ini juga terdapat talk sesion bersama Ayu Suma, designer & conceptor dari Indira Laksmi dengan Idon Pande sebagai moderator. Dalam sesi ini Ayu Suma menyampaikan bahwa pameran ini adalah perayaan untuk proses mereka di Indira Laksmi. “membuat acara ‘From Sketch To Soul’ ini adalah perayaan untuk proses kami, jadi merayakan perjalanan kami. Dari proses ini kami menceritakan bahwa di Pameran proses tadi, Indira Laksmi ini tidak hanya menciptakan suatu karya yang indah tapi juga memikirkan bagaimana karya ini bisa menyentuh jiwa dan emosi dari klien yang akan memakainya.” Jelas Ayu Suma dalam talk sesion pameran.
Ayu Suma menyampaikan tantangan selama berkarya adalah dalam memadukan rasa antara desainer, klien, dan photographer yang memiliki karakteristik yang berbeda karena Indira Laksmi berhubungan erat dengan ketiga elemen tersebut. “Sebenernya proses berkarya itu, kesulitannya adalah dalam menyatukan rasa antara kami yang mendesain, dengan klien, dan si photographer. Karena jujur Indira Laksmi, hubungannya dengan tiga hal itu.” Terang Ayu Suma. Hal tersebut menjadi tantangan untuk menghasilkan sebuah karya yang sempurna.
Ayu Suma juga menyampaikan bahwa sebuah sketsa dikatakan sudah layak diwujudkan ketika semua sudah satu rasa antara proporsi tubuh klien, estetika, warna, hingga perpaduan motif. Ketika elemen tersebut sudah satu rasa, maka sebuah sketsa dapat dikatakan layak untuk diwujudkan.
Beberapa tamu yang hadir juga menyampaikan kesan mereka selama mengikuti house tour. Nazmi salah satu tamu yang hadir mengatakan “saya pertama kali melihat Indira Laksmi dari Instagram, saya dari Tabanan datang ingin melihat bagaimana proses kreatif dari Indira Laksmi. Satu benang memiliki filosofi yang mendalam bagi saya”.
“saya benar-benar merasakan aura yang dikeluarkan dari sejarah kain. Dalam artian Indira Laksmi benar-benar menggali sejarah dari leluhur kita, trus dijadikan sebuah kain. Selain menjaga, Indira Laksmi juga membentuk kain baru seperti Bapang, Jatayu. Tidak semua orang bisa mengekspresikannya menjadi sebuah rasa.” Ujar Maha Made, salah satu tamu yang mengikuti pameran ini.
“Yang paling saya rasakan itu pertama kali, bangga banget sama Indira Laksmi. Melihat perkembangannya sangat pesat, saya selalu merasa disini sudah seperti rumah.” Ucap Nindi, salah satu tamu dari pameran Indira Laksmi dalam talk sesion yang membagikan kesannya.
Bagian yang paling dinantikan oleh Ayu Suma adalah respon dari para tamu yang hadir dan mengikuti pameran ini terhadap karya-karya Indira Laksmi. “sebenarnya yang paling saya nantikan adalah respon kalian terhadap karya-karya kami di atas, yang kami kerjakan bersama-sama, responnya apakah berhasil atau bagaimana.” Ungkap Ayu Suma.

Setelah talk sesion, dalam sesi Story Behind the Sketch, menampilkan kisah pendek tentang inspirasi di balik beberapa karya dengan ditayangkannya video dokumenter Idup Panak. Setelahnya dilanjutkan dengan Art perfoming by kitapoleng, live Sketching by Ayu Suma, dan digital mapping by Almarira & Kokoksaja, closing permomance dari pameran ini adalah penampilan live acoustic by Gung Doni & Friend.
Melalui pameran ini Ayu Suma ingin memperlihatkan kepada tamu bagaimana proses dari Indira Laksmi, merasakan bagaimana Indira Laksmi berproses. Bukan hanya menghasilkan karya yang indah, tapi juga melewati proses yang panjang. Dari penggambaran sketsa sampai dengan proses fitting dengan klien. Banyak warna dan aksesoris yang dipadukan untuk membuat klien terlihat cantik nan menawan.
“Halo, Aku adalah interpretasi dari apa yang kalian inginkan, dari warna, dari karakter, dari emosi yang kalian inginkan, dan aku siap jadikan kenyataan.” –Ayu Suma, saat menjawab pertanyaan “jika sketsa bisa bicara, cerita apa yang ingin mereka sampaikan?” []
G.A. Made Widiadnyani
“hai..hai...” Naira, bocah perempuan meneriaki Fari dan Rafi yang sedang sibuk berlarian,berkejaran.
“Ahh…” Fari bergumam, sambil tak memperdulikan Naira dan terus mengejar Rafi.
Matahari menggantung tepat di atas kepala, hamparan rumput hijau luntur, debu terbang menempel pada keringat, pada wajah hitam terbakar siang.
Sebuah botol diselipkan di sisi roda sepeda mungil, suara yang dihasilkan memicu semangat Fari untuk semakin cepat mengayuh. Sementara Rafi dan Naira kini tertawa melihat ekspresi Fari yang terus mencoba menghasilkan suara nyaring menyerupai knalpot motor bersuara nyaring, knalpot 2 tak, khas brandalan desa.
Perempuan tua duduk di sebuah bale yang diletakkan di bawah pohon juwet. Lokasi teduh yang menjajikan hembusan angin. Siapa yang kuat di dalam rumah, ketika ruangan telah menjadi sauna yang memeras keringat. Beberapa ekor sapi melintas, menghidari paparan matahari, mencari rumput yang lebih hijau, lebih berair. Dahaga lebih menyiksa dari pada lapar.
Di sebuah pondok berdiri di utara ujung halaman, menjadi sebuah posko pemantau. Semua yang melintasi padang rumput akan terlihat jelas. Pekerja pabrik dengan helm kuning, pelindung kepala dari benturan, namun sayangnya tidak cukup mampu untuk melindunngi kepala dari susupan akan kenyamanan yang disuapkan. Sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda tajam tapi tak membuat langkah lebih ringan. Seragam yang membuat mereka tampak lebih gagah, tetapi kehilangan kepekaan untuk tergugah. Pegawai pabrik yang sering melintasi padang rumput yang mereka ciptakan. Padang rumput yang kian hari kian gersang.
Pasak-pasak raksasa teronggok, tersusun di salah satu sudut tanah lapang,tersusun rapi. Sementara reruntuhan bangunan menjadi ornamen yang menghiasi padang rumput. Jejak rumah, jejak keluarga yang kalah, menyerah, kalah. Puing-puing kekelahan yang belum ditelan kekuatan tamak kemajuan jaman.
Dan bocah-bocah berlarian di antara puing, ornamen kekalahan dan rumput yang kian hari semakin pudar.
“Fari...” perempuan tua itu memanggil “taruh sepedanya!” perintahnya.
Perintah yang lahir dari kalimat, kalimat yang tak dihiraukan.
Fari semakin cepat mengayuh, semakin menjauh meninggalkan halaman, suara yang dihasilkan semakin nyaring.
“ayo cepat” suara Rafi tidak sabar, meminta Fari kian cepat mengayuh. Tidak sabar menanti giliran.
Sementara Naira hanya tertawa melihat kelakuan kakak-kakak sepupunya.
Perempuan tua itu hanya bisa melihat bocah-bocah kecil pembawa kecerian ke halaman rumah. Halaman rumah yang kian kering dan gersang.
Dia tak bisa membayangkan betapa sepi rumahnya jika tidak ada cucu-cucunya itu. Betapa sunyi rumahnya jika dia hanya hidup dengan sang suami,lelaki yang tidak kalah lelah, tidak kalah renta,tidak kalah keriput.
Lelaki tua yag telah kehilangan ketegapannya, yang hannya bisa duduk di pondok dibawah pohon asam, sambil melihat semua yang melintas dihadapannya. Sesekali menyalurkan keisengannya, menggunakan ketapel untuk membidik sapi tetangga yang coba masuk ke pekarangan, masuk untuk menikmati rumput yang tampak lebih hijau dari kejauhan.
Bocah-bocah itu masih berlarian, kini sepeda tidak lagi di bawah kendali Fari. Pedal sudah berada di bawah kaki Rafi,yang tidak kalah kencang mengayuh, memacu sepeda dengan suara nyaring hasil gesekan roda dengan botol air mineral yang disepilkan, melaju kencang menuju sisa-sisa reruntuhan.
“kak Rafi…” Naira berteriak, memberi semangat, mencari perhatian. Fari menatap sodaranya memacu sepeda. Memandang, terengah, dengan keringat dipelipis dan wajah hitam terbakar.
“sudah,berhenti dulu!” perempuan tua berteriak.
Teriakan yang tak lagi dihiraukan, tak pula cukup kuat untuk membuat ke tiga bocah itu berhenti melakukan yang mereka suka.
Suara yang keluar,seberapapun kerasnya tetap saja hanya sebuah suara perempuan tua. Seperti halnya tangan dan jemari yang telah dirayapi waktu, berkerut, keriput.
Demikian pula dengan pita suaranya. Pita suara yang kian mengendor, meleleh, membuat suaranya tak lagi bisa selirih dan lantang dahulu. Tidak lagi sekuat ketika nafas masih panjang, lengan masih kencang mengontrol jemari untuk cekatan melakukan semua pekerjaan.
Tidak lagi seperti ketika bahu masih kencang membahu, melihat semua celah mengambil kesempatan demi bisa bertahan dan menghidupi anak-anak yang lahir dari rahimnya. Menghidupi anak-anak yang kini telah memberikannya cucu-cucu.
Salah tiganya, cucu-cucu yang kini ada dihadapannya. Berkeliaran bermain dihadapannya. Berlarian di halaman dengan asik bermain, di tengah terik hingga tak lagi mendengar nasehan, arahan dan kekhawatiran yang diteriakkan.
Tiga orang bocah yang tidak pernah sempat melihat bagaimana perempuan tua yang sedang mengawasinya tersebut membesarkan orang tua mereka. Terjaga sebelum kumandang adzaan subuh, yang kemudian dalam sunyi mengumandangkan keyakinan akan harapan untuk orang tua mereka yang masih terlelap. Menghadirkan sarapan di meja makan yang siap disantap, ketika orang tua mereka baru membuka mata dan memutuskan turun dari tempat tidur.
Lalu ketika orang tua mereka pergi mengenakan seragam, menuju ruang-ruang kelas yang menertibkan, perempuan tua itupun melangkah meninggalkan rumah, menuju ladang.
Sepetak tanah yang diwarisi dari mertuanya, warisan yang didapatkan sang mertuanya dari mertua sebelumnya. Demikian sepetak tanah yang kini masih didiaminya turun, dari beberapa generasi di atas diturunkan hingga kini dan kemudian nanti ke cucu yang kini sedang berlarian di sekitar petak tanah terssebut.
Hal tersebut akan berlangsung, jika tenaga dan suaranya masih bisa terdengar sekuat keyakinan dan imannya, dan jika anak-anaknya memiliki keyakinan dan iman yang serupa.
Pada akhirnya dia hanya perempuan tua, yang semenjak kelahiran pertamanya mendedekasikan hidupnya untuk kehidupan anak dan anak-anak yang dilahirkan oleh anak-anaknya. Dan apapun yang dimilikinya pada akhirnya akan diserahkan pada anak-anaknya, kecuali luka dan duka, yang disimpan rapat. Disimpan jauh di dalam belulang yang terbungkus otot dalam kulit yang kian berkerut.
Hingga kini ketika otot-otot mengendur dan kulit meleleh, luka dan duka tetap dikuncinya rapat-rapat.
Bahkan ketika kini suaranya tak lagi cukup dihiraukan, cukup dihiraukan untuk membuat ketiga bocah itu meringkuk duduk di dipan di bawah pohon sambil menunggu terik berlalu, dia masih setia menjaga anak-anak dari anaknya, menjaga agar mereka baik-baik saja. Baik-baik saja dalam menikmati permainan yang menggembirakan mereka.
“Kak Rafi... Kak Rafi” Naira berteriak, dengan huruf r belum terucap dengan tegas.
Rafi masih asik mengayuh sepeda di atas lantai yang tersisa. Lantai yang telah ditinggalkan, lantai yang masih tampak jelas.
Sisa lantai rumah dari mereka yang dahulunya menjadi tetangga. Sisa lantai dan sisa dinding yang telah menjadi puing. Sementara bangunan lainnya telah rata dengan tanah dan menjadi lapang ditumbuhi rumput. Rafi dan Fari, 2 bocah yang masih setia bermain di area tersebut, sesekali Naira ikut menambah keceriaan dan keriangan. Naira hanya bisa bermain bersama kedua kakaknya ketika salah satu atau kedua orang tuanya datang mengunjungi neneknya. Seorang perempuan tua yang masih setia menjaga tanah,tempat dia tumbuh. Tanah yang diwariskan ke padanya. Tanah yang menjadi ruang dia merawat keluarganya.
Satu persatu tetanga merelakan warisannya. Meninggalkan tanah merelakan rumah. Ganti untung tiba bersama dengan serangkaian mimpi yang dihembuskan tentang tanah baru. Rumah baru. Mimpi yang mekar seiring nominal rupiah yang masuk dalam rekeing, dengan jumlah nol tidak sebanyak biasanya. Nominal yang hadir sebagai kompensasi atas tiap jengkal amanah, tiap inchi ingatan, dan cerita terampas.
Nominal menjanjikan tanah baru, rumah baru dan cerita baru.
Dan kaki harus diangkat, langkah harus diayun dan warisan, amanah dan segala ingatan harus ditinggalkan. Mimpi dan harapan baru harus disosngsong.
Dan di depan kerugian meyambut. Kerugian utama tentu rasa bersalah telah melepaskan amanah. Amanah dalam bentuk tanah waris yang harusnya mereka jaga untuk kemudian bisa diteruskan kepada anak-anak yang lahir setelahnya. Warisan yang dimanatkan untuk generasi yang lahir kemudia, generasi-generasi yang kemudian menjadi dahan dan batang pohon keluarga mereka.
Penyesalan pertama yang harus mereka ratapi di balik dinding-dinding rumah baru,hasil penggantian tanah dan bangunan mereka.
Penyesalan bahwasanya kini mereka harus hidup di tempat yang baru, dengan kebiasaan yang baru kemudian menyusul. Keluarga di depan rumah yang dahulu bisa diajak berbagi lelah kini sudah tak ada lagi. Berganti dengan keluarga yang belun dikenal dan tak tahu apakah mereka punya telinga yang sama, punya mulut yang sama, punya hati yang sama untuk kemudian ikut bersama-sama merasakan bagaimana hari yang dilalui begitu melelahkan.
Penyesalan yang kian menghimpit ketika mendapati rupiah yang didapat kian menipis setelah terkuras oleh apa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Terkuras oleh segala ingin yang selama ini menjadi angan yang diidam-idamkan dan membuat mereka semakin giat bekerja untuk mewujudkannya.
Bahkan ketika beberapa angan berhsil mereka wujudkan, mereka tidak lagi tahu apa yang harus dikejar dan bagaimana mengejarnya, ketekunan dan kerja keras seolah menguap setelah mimpi tak lagi menjadi mimpi. Dan bahkan ketika mimpi yang berhasil diwujudkan rasanya tak seperti dalam bayangan, sebagaimana ketika mimpi itu masih berupa sebuah impian.
Sementara kesederhanaan telah roboh tepat ketika bangunan-bangunan yang berhasil dibangun dengan ketekunan dan keuletan roboh oleh buldoser kemajuan yang dijanjikan.
“nek,ada roti?” Fari tiba-tiba bertanya pada perempuan tua yang melempar pandangannya jauh ke kompleks bangunan beratap genteng yang masih terlihat coklat.
“minta sama ibu sana” jawabnya. Tidak ada sesuatu yang bisa langsung didapat dengan sekali minta.
“aduh,fari males minta sama ibu” Fari memohon “ada ndak nek?”
“ada, ambil di toples dikamar nenek” belum lagi kalimatnya selesai Fari sudah berlari meninggalkan perempuan tua itu “ambil juga buat adik-adikmu”.
“iya” teriak Fari.
Naira hanya melihat kakak sepupunya berlari masuk ke dalam rumah. Bayangan pohon memanjang ke barat. Perempuan tua itu mengalihkan pandangannya, dilhatnya Rafi masih asik dengan sepedanya dan puing-pung rumah tetangganya.
Ada ingatan bagaimana dahulu mereka bisa saling berbagi obrolan diteras rumah itu. Berbagi cerita tentang sayur apa yang dia masak, tentang ikan yang bisa digoreng, tentang cabai dan sayur yang bisa dipetik. Tentang rumput yang paceklik, tentang biaya anak-anak sekolah yang mencekik.
Ada kekhawatiran yang melintas, sampai kapan dia akan kuat mempertahankan amanat ini, sampai kapan dia bisa menjaga keyakinannya, sampai kapan anak-anaknya akan mendengar suaranya. Bukankah kemajuan dan iming-iming hidup yang lebih baik selalu lebih manis dari apa yang sebenarnya harus ditanggung. Di tengah tubuh yang kian merenta, nama obat yang kian panjang ditulis di kertas resep, nafas yang kian sesak, suara akan menjadi semakin kecil. Apalagi jika pada kenyataannya panen dari sepetak kebun telah menghanatinya.
Kekhawatiran yang terpancar dari matanya, bertahan adalah pilihan yang berat. Bertahan menjaga amanat selalu berat, lebih berat dari pada ketika menginginkan dan akhirnya bisa menggenggam amanat tersebut.
Apalagi ketika bertahan menjaga amanah, warisan yang diwariskan dengan bersading, bertetangga sebuah cerobong raksasa yang dengan konsisten menghembuskan asap abu-abu ke angkasa.
Racun yang terus dihembuskan ke udara mengiringi deru mesin yang terus menyala. Sementara usia menua otot pernapasan kian renta, tubuh harus ditopang dengan rutin menyambangi dokter dan menebus daftar obat yang terus bertambah. Sementara kondisi tubuh terus menurun, biaya kesehatan kian naik dan harus ditanggung sendiri. Sementara keyakian harus terus ditenenun, udara terus diracuni. Dan perempuan tua itu harus tetap bertahan dalam kubangan yang kian mengering.
“Rafi” Fari memanggil adiknya dengan mulut telah berisi segigit roti. Menunjukan roti yang dia ambilkan untuk adiknya. Roti ditangan Naira juga telah menyapa bibirnya.
Rafi mengayuh sepeda menghampiri kakanya “kamu mau?” Rafi menawarkan sepedanya pada sang kakak.
“tidak. kamu aja” jawabnya pendek.
Perempuan tua itu seoalah telah kehilangan seleranya pada makanan. Bahan makanan yang dahulu bisa didapatkan dengan mudah dari kebun atau dibawa dari laut oleh suaminya kini seolah menjadi dongeng.
5 tahun kehadiran tetangganya, sebuah PLTU Batubara telah berhasl merenggut segalanya. Tanah yang subur, laut yang makmur kini hanya menjadi hikayat dalam syar-syair puitis penyair gombal.
Ladang yang bertahun-tahun menghidupi dia dan keluarganya kini telah mengering, air yang dibawa akar-akar pohon untuk mengisi sungai telah lama menghilang seiring hilangnya pohon-pohon yang dibabat untuk persiapan lahan pembangunan PLTU tahap ke-2.
Haya cekungan-cekungan kering yang ditumbuhi perdu dan lembab akibat sisa huja yang terperangkap. Kelapa yang setia menyusuinya setiap dua bulan kini telah menghianatinya, sudah 4 bulan dia harus melalui hari tanpa sebutir kelapa yang bisa dia uangkan. Laut yang dahulu selalu membiarkan anaknya memanen ikan kini lebih sering mengembalikan putranya, pulang ke rumah setelah seharian terombang-ambing dengan tangan hampa, tanpa seekor ikan pun.
Tapi amanat terus harus dijaga, keyakianan tetap harus dirawat, meski dia tahu racun juga harus terus dia dan keluarganya hirup.
“sudah kalian mandi, lalu masuk rumah” perempuan tua itu menyuruh ketiga cucunya. Menyadari semakin lama mereka berada dihalaman, semakin banyak pula racun yang dihembuskan PLTU harus mereka hisap.
Racun yang harus dihisap oleh Naira, Fari dan Rafi. Adalah racun yang sama yang harus dihisap oleh si perempuan tua. Bahkan suaminya ,anak-anaknya, anak dari anak-anaknya dan bahkan cucu dari cucu-cucunya akan menghisap racun yang sama, racun yang hadir dan menjadi tetagganya. Menjadi tetangga tanpa tanta meminta ijin, hadir memaksa dan terus dia tolak hingga hari ini.
L.Taji
“apa yang kau masak hari ini?”
Tentu saja pertanyaan itu datang begitu saja, danatang walau tidak kemudian menggetarkan genderang telingaku. Suara mesin gerinda di belakang rumah begitu jelas, keras terdengar, sibuk sedari pagi memotong besi. Suara gerinda sibuk itu telah terlebih dahulu menguasai gendering telingaku.
Pertanyaan itu hadir begitu saja. Sementara telingaku sedang sibuk dengan alunan music yang tidak akan kau suka. Musik yang aku putar untuk menyamarkan suara gerinda. Menyamarkan kendaraan yang melintas hilir mudik, gonggongan anjing, suaran gerbang biru yang dibuka-tutup oleh penghuninya yang sibuk, sibuk keluar masuk.
“apa yang kau masak hari ini?” itulah pertanyaan yang datang begitu saja.
Seperti seekor kadal yang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Atau seekor anak cicak yang melintas di bawah gelas kopi yang terongok beberapa hari. Entah itu kopi hari apa, aku lupa, yang aku tahu dia telah berubah fungsi menjadi rumah untuk sekoloni jamur.
“aku belum memutuskan” jawabku. “yang jelas hari ini aku tak akan memasak keringatku” lanjutku.
Tidak ada pertanyaan susulan. Hanya gonggongan seekor anjing terdengar sayup-sayup mengejar kendaraan yang melintas. Sayup-sayup diantara suara gerinda dan alunan musik memutar lagu selanjutnya.
Keringatku belum cukup untuk bisa dimasak, walau dia merembes keluar dari pori-pori namun tetap saja masih tidak cukup.
Hujan yang hadir dengan semena-mena membuatnya begitu cepat larut dan luruh bersama lumpur yang bangkit, mengalir menyapa akiku. Mengalir menuju selokan.
“Keringatku belum cukup untuk bisa aku masak hari ini”
“lalu apa yang akan kau masak hari ini?” pertanyaan itu kembali datang, tidak puas dengan jawaban yang kuberikan.
“aku belum memutuskan!” jawabku tegas.
Untuk apa tahu tentang apa yang akan aku masak hari ini. Untuk apa tahu tentang apa yang akan aku makan hari ini. Aku tak ingin memberitahukannya.
Tanah masih basah, hujan lebat semalam hingga pagi tadi masih menyisakan jejaknya. Sementara speaker sedang memutar lagu selanjutnya, lagu yang tidak aku tahu judulnya, namun aku tahu kau tidak akan suka.
Aku memutarnya hanya untuk menyamarkan suara kendaraan yang melintas. Menyamarkan suara perempuan di belakang dinding yang tak pernah lelah memarahi anaknya. Marah akibat si anak tidak segera mandi, atau mengompol, atau susah disuruh makan. Atau ratusan alasan lain untuk marah. Ratusan alasan agar dia bisa marah.
Mungkin saja amarah itu bisa menjaganya tetap waras dan masih bangun pagi dan menyiapkan ratusan keperluan anak-anaknya.
Pertanyaan itu tidak muncul. Namun kini suara perempuan di belakang dinding kian meninggi dan bertubi-tubi. Seperti berondongan senapan mesin yang ditembakkan dengan dendam.
Volume musik aku besarkan, aku tidak ingin mendengar berondongan amarah. Juga tak mau mendengar tembakan pembalasan yang akan kian membabibuta. Berondongan amarah balasan yang akan menyusul kemudian.
Biarkan saja instrument yang tak aku mengerti itu memenuhi telingaku.
Aku duduk dengan segelas kopi yang aku buat siang tadi. Dengan gelas lain yang aku letakkan di sebelah segelas kopi yang telah hadir terlebih darulu. Segelas kopi dengan jamur mengambang di permukaannya. Teronggok begitu saja di salah satu sudut ruang keluarga.
Ruang keluarga yang bahkan telah lama kosong, ditinggalkan. Mereka telah pergi untuk berlari mengejar mimpi-mimpi mereka.
Jamur mengambang dari sisa kopi yang entah telah berapa hari aku abaikan. Aku ingin membiakkannya, siapa tahu itu adalah jamur yang bisa membuat mimpi-mimpi bisa terlupakan. Sehingga tak ada lagi yang perlu berlarian, berkejar-kejaran mengejar mimpi dan pada akhirnya saling meninggalkan. Berakhir untuk saling meninggalkan.
Tentu saja keinginan itu akan kalah oleh kenyataan, aku perlu gelas untuk setiap kopi pahit yang aku butuhkan untuk mengawali hari. Melewati hari di rumah ini. Menikmati waktu bersama ruang keluarga yang kesepian setelah ditinggalkan keluarganya.
Gerbang biru terdengar dibuka, lengkap dengan suara penghuninya yang melengking tinggi.
Aku ingin membesarkan volume musikku, namun hari telah gelap. Akan ada dua teriakan yang silih berganti menghimpitku dari depan dan belakang. Apa yang sebenarnya mereka banyangkan dengan teriakan teriakan yang mereka pekikkan.
“apa kau akan memasak hari ini?” pertanyaan itu kembali. Pertanyaan yang berubah dari sebelumnya.
Aku tidak ingin langsung memutuskan untuk menjawabnya. Bisa jadi pertanyaan itu adalah sebuah perangkap untuk pertanyan-pertanyaan selanjutnya yang tak akan pernah berhenti. Pertanyaan yang akan memancing aku harus mengungkapkan apa yang hendak aku lakukan dan kenapa melakukan itu.
Atau aku tidak menjawabnya karena memang aku tidak ada gambaran apakah aku akan memasak atau tidak hari ini.
Sejujurnya sudah beberapa hari ini aku tidak memasak. Ada persoalan api yang tak mau menyala. Bahkan ketika gas melon telah berhasil aku isi ulang, sebagai sumber energi bagi si api bisa kembali menyala. Belakangan niatku hanya berhasil sebatas membuat air panas.
Hanya air panas untuk kopi. Sama rebusan daging giling untuk anjing yang tak tahu diri. Serta menghangatkan opor dan rendang instant kemasan yang dikirimkan sebagai hadiah hari raya tahun ini.
Itu tentu tidak masuk dalam kategori memasak.
Sebatang rokok lembab aku ambil dari dalam bungkus rokok yang berserak di lantai. Bungkus rokok yang berjuang keras untuk tetap menjaga sebatang rokok tetap kering. Usahanya berhasil secara citra. Paling tidak rokok itu masih putih mulus tanpa bercak kecoklatan yang akan membuat muak untuk membakarnya.
Namun belum lagi aku menghembuskan asap hisapan pertama dari sebatang rokok yang berhasil diselamatkan oleh sebungkus kertas rokok, pertanyan datang kembali “jadi apa kau akan memasak hari ini?” Kembali hadir begitu saja, seenaknya.
Pertanyaan yang membuatku tersedak.
Sebuah rice cooker buluk teronggok menganga di hadapan kulkas penuh stiker. Aku melihatnya dengan seksama. Melihatnya sambil bersandar pada dinding yang tak mampu meredam lengkingan suara perempuan yang datang dari belakang rumah. Menatapnya, hanya menatapnya.
Apakah rice cooker itu yang sedang melempar pertanyaan padaku?
Jika dia yang melemparkannya, dia seharusnya sudah tahu jawabannya.
Bukankah itu kebiasaan hari ini, melempar pertanyan yang jawabannya sudah diketahui dan sudah berada dalam genggaman. Bertanya bukan untuk mencari tahu, namun untuk memamerkan apa yang diketahui.
‘Ahh, tidak mungkin rice cooker akan melakukan itu’ pikirku diantara asap yang mengepul dari sebatang rokok kretek lembab. Asap hembusan kedua yang jauh lebih nikmat dari hembusan pertama yang kacau oleh pertanyaan.
Aku masih belum beranjak, menikmati sebatang rokok lembab yang berhasil aku temukan di antara serakan bukus rokok kertas favoritku. Duduk bersandar sambil menyeruput kopi dari sebuah gelas yang belum direbut oleh jamur. Belum direbut dan dikuasai oleh kemalasan dan pengabaian.
Aku belum beranjak, masih memandang ke setiap sudut ruang. Serakan pakaian, beberapa selebaran, kursi, dan benda-benda yang sejujurnya aku tidak paham untuk apa harus disimpan.
‘ini ruang keluarga dimana seharusnya gelak tawa dan cengkrama terjadi. Namun alih-alih menyebutnya sebagai ruang keluarga, ruang ini tak lebih dari ruang kesepian. Jadi biarkan saja barang-barang itu hadir, menguasai, meramaikan. Meramaikan kesepian ruang keluarga yang telah ditinggalkan oleh keluarga yang menghadirkan ruang ini, sebagai ruang keluarga’ pikir ku.
Setengah gelas telah habis, setengah batang dari sebatang kretek lembab itu juga telah jadi abu.
‘baiklah aku akan memasak hari ini’ kataku dalam diri, sebelum beranjak dari posisiku. Berdiri dan melangkah dengan setengah batang rokok lembab dan setengah gelas kopi.
Berjalan menuju dapur.
“apa yang hendak kau masak hari ini?” pertanyaan datang lagi. Sebuah pertanyaan bawel yang begitu amat teguh mengejar keingin tahuannya.
“biarkan aku sampai dapur dahulu” kataku. “Setelah itu akan aku putuskan” lanjutku menjawabnya.
Mengambil ulekan yang tertelungkup di sebelah korakan, bercak jamur begitu jelas terlihat. Bercak jamur yang tumbuh akibat pengabaian yang berlangsung. Jamur yang terpaksa harus disingkirkan lewat kucuran air yang menetes perlahan.
Ulekan ditengadahkan.
Sebuah wajan yang telah mengering di rak perabotan masih menyisakan jejak kerak pada pantatnya. Sudahlah, itu riwayat, siapa yang bisa menghapusnya?
Yang bisa aku lakukan hanyalah menerimanya. Menerima setiap jejek kerak yang masih melekat, menerimanya sebagai riwayat kisah, riwayat perjalanan.
Aku menghitung amarahku, menghitung dengan seksama. Ya, aku menghitungnya dengan seksama. Bahkan ketika amarah itu telah keriput dan mengering dalam dingin ruang penyimpanan bawah sadar.
Yang begitu dingin. Begitu dingin mengeringkan.
Aku menghitungnya dengan seksama, mesatikan dalam bilangan ganjil. Mengikuti nasehat seorang ibu warung yang berkata, “pedasnya cabai itu nikmat jika berjumlah ganjil”
Bukankah amarah juga seperti itu? Dihitung dengan seksama dalam hitungan ganjil, dengan keganjilannya.
Aku melempar amarah itu dalam ulekan.
Kemudian menambahkan secumput kecil asin, hanya sejumput kecil duka, sejumput kecil saja, akan pengalaman duka yang dialami.
Aku harus hati-hati pada asin, asin akan melahirkan potensi emosional dan tentu saja kekentalan darah. Aku juga takut rasa asin pengalaman yang berlebih membuat rasanya tidak lagi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Membuatnya menjadi pahit.
Berelebih akan menghadirkan selain emosiaonal akibat kekentalan darah juga kebas di lidah, yang akan membuat kepekaan akan rasa menjadi sirna.
Serangkaian perjalanan waktu dan proses saling belajar, yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bersama untuk saling jujur telah diinjak-injak, menjadi bangkai. Diinjak-injak dengan dendam dan pembalasan, lalu kemudian dikemas sedemikian rupa dalam bentuk pembenaran diri.
Aku ingin menghadirkannya, dan harus menghadirkannya.
Secuil terasi, rasa sederhana. Butuh sedikit saja, untuk mengingatkan akan bagaimana rentang proses dan perjalan itu diabaikan dan dirubah begitu saja untuk kemudian dihadirkan dalam bentuk baru (pembenaran). Terasi adalah rasa yang hadir dari serangkaian pengorbanan dalam serangkaian rentang proses perjalanan.
Sebuah limau aku iris. Untuk memastikan, luka itu adalah perih yang harus diingat dan dirasakan.
Dalam ulekan mereka terbaring dan siap untuk dikoyak-koyak.
Ulekan melakukan tugasnya, mengoyak semua yang terbaring dalam kuasanya, mencampurnya, menghaluskannya.
Menjadikan hitungan amarah, asin pengalaman, pengingkaran pengorbanan dan perihnya luka menjadi sebuah kesatuan.
“jadi apa yang kau masak hari ini?!” pertanyaan itu masih bertanya.
Api telah aku nyalakan. Wajan dengan kerak di pantat yang tak bisa aku hapus telah aku letakkan di atas nyala api. Sedikit minyak aku tuang dalam wajan.
Pada tunggku satunya, aku coba menyalakan api yang lain. Kletek…mati, kletek…mati, kletek… mati…
Kletek, akhirnya menyala. Sebuah panci dengan air aku letakkan di sana.
Minyak telah mendidih. Potongan kenyataan harus aku iris dan aku lempar dalam wajan.
Potonngan kenyataan. Potongan penuh lemak dan daging tanpa tulang.
Aku mengirisnya, mengirisnya sendiri untuk aku lempar kedalam wajan dengan minyak yang memanas.
Aku memilih irisan kenyataanku, satu irisan aku pikir cukup untuk kebutuhanku hari ini.
Jadi aku lempar dalam wajan dengan minyak panas itu, membiarkan irisan daging kenyataan mulai gemericik mengeluarkan minyak dan airnya.
Aku menunggu, sambil coba untuk mengumpulkan apa yang telah aku ulek.
Sial air dalam wajan di tungku sebelah telah mendidih, sementara irisan daging masih menunggu waktu.
Aku melempar harapan dalam air mendidih.
Melemparnya dalam air mendidih, sambil coba berusaha memastika harapan masih tetap segar.
Irisan kenyataan, yang terabaikan telah matang, airnya telah menguap. Sementara minyaknya keluar sedemikan rupa.
Itu adalah daging tubuhku.
Ketika aku tak bisa memasak keringatku, lalu apa yang bisa aku masak?
“jadi sebenarnya, apa yang kau masak hari ini?” pertanyaan itu muncul lagi.
Aku diam. ‘aku sudah coba kembali masak, dan kau masih saja tetap bertanya’ pikirku.
Memasak bukan urusan untuk menjawab pertanyaan, memasak soal keinginan untuk memasak, keinginan untuk melakukaknya.
“Jadi, apa yang kau masak hari ini?” kembali pertanyaan itu muncul.
“bangsat, aku memasak kesepianku” kataku menjawab.
“hari ini aku memasak kesepianku” jawabku. “memasak kesepianku!” lanjutku tegas.
“Kesepian yang seharusnya aku rasakan 7 tahun lalu, namun pada kenyataannya aku ingkari lewat serangkain pelarian penuh omong kosong. Dan dia kembali hari ini” aku memutuskan menjelasakan.
“Serangkaian pengingkaran yang kemudian harus membuatku kembali ke titik nol. Kesepian dan kesendirian 7 tahun lalu yang harus aku maknai, namun aku berpaling dan memilih untuk berlari, enggan menghadapinya” lanjutku.
Dan hari ini pada kenyatannya aku sedang memasaknya.
“aku sedang masak kesepian dan seksendiarianku” jawabku. “apa kau puas dengan jawabanku?” lanjutku.
“Apa kau puas dengan jawabanku?” aku bertanya balik.
“Apa kau puas dengan jawabanku??” teriakku, bertanya menghardik.
Hening, takda jawaban yang hadir.
Dari depan, teriakan perempuan kencang menghardik bocah, anaknya. Di belakang, perdebatan dengan nada tinggi, kian tinggi menggema.
Suara gerinda masinh nyaring, menderit. Gonggongan anjing jika keras menyalak. Volume perlu music perlu ku naikkan, untuk menghadapi himpitan suara yang kian cepat dan meninggi.
Dan menikmati masakan yang berhasil ku masak, masakan yang tak akan enak untukmu. Karena ini masakanku, yang akan ku santap, ku nikmati untuk menghidupi dan menumbuhkanku.
Irisan luka, dalam bumbu duka, tersajikan dalam baluran saos sepi. Ada bercak hijau harapan, aksen tipis. Dan tentu saja bawang goreng omong kosong.
Itu yang berhasil aku masak, aku hadirkan.
Kenyataan berhasil hidup, hadir untuk aku santap hari ini.
“lihat, lihatlah masakanku. Kau meu mencicipinya?”
Tak ada suara yang muncul.
Si Penanya yang hadir dengan pertanyaan, “masak apa hari ini?” hilang. Hilang ditelan riuh kenyataan.
l.taji
13.01.25
Cokorda Gede Oka Geg, raja terakhir Kerajaan Klungkung. Begitu perang puputan usai ( 1908), ia beserta keluarga dibuang ke Lombok. Belanda lalu mengambilnya kembali untuk disekolahkan ke Jawa. Pada tanggal 1 -7-1929, oleh Gouverneur General van Nederland Indie ia diangkat menjadi Zelf bestuur der Landschap Klungkung dengan Ambts titel Dewa Agung.
Di samping sebagai raja, beliau dikenal sebagai seniman serba bisa. Penari gambuh yang andal. Ada sejumlah seniman di Klungkung dan Gianyar pernah ikut menari dengan sang raja. Sebut misalnya, Dadong Lemon, penari arja terkenal dari Tegal Linggah, Desa Bedulu, Gianyar. Mengaku dalam wawancara saya pernah menari dengan sang raja.
 Ada banyak catatan sejarah tentang raja ini, baik dari sumber-sumber Belanda maupun sumber-sumber lokal. Saya tak hendak bercerita soal ini, maklum saya bukan orang sejarah. Tentang raja ini berserakan kabar lisan yang masih bisa kita simak, alih-alih bagaimana kebijakan raja menghadapi pandemi. Tentu cara sang raja tidak boleh dianggap ilmiah, dan tak lucu dipertentangkan dengan capain-capain sains hari ini.
Ada banyak catatan sejarah tentang raja ini, baik dari sumber-sumber Belanda maupun sumber-sumber lokal. Saya tak hendak bercerita soal ini, maklum saya bukan orang sejarah. Tentang raja ini berserakan kabar lisan yang masih bisa kita simak, alih-alih bagaimana kebijakan raja menghadapi pandemi. Tentu cara sang raja tidak boleh dianggap ilmiah, dan tak lucu dipertentangkan dengan capain-capain sains hari ini.
Suatu hari di Geria Banjarangkan, saya mewawancari Ida Pedanda Putra Telaga, mantan Ketua Umum Parisada Indonesia, tahunnya saya lupa. Menurut Ida Pedanda, raja ini seperti dikaruniai banyak keajaiban. Saat karya Eka Dasa Rudra di Besakih, tahun 1963. Raja tengah muspa di Penataran Agung, tiba-tiba Gunung Agung mau meletus. Saat itu sang raja hanya bisa memohon pendek pada Bhatara Gunung Agung, "Mbok tiang kari muspa, sampunang mamargi mriki ( Mbok saya masih sembahyang, jangan lewat ke sini). Itu kata-kata raja yang didengar pengiringnya.
Apa yang terjadi kemudian? Letusan Gunung Agung memang tidak melewati Pura Besakih, dan raja tetap suntuk memuja di kaki Gunung Agung yang saat itu tengah memuntahkan lahar. Ini kabar lisan yang pernah saya dengar dari tetua di Klungkung. Termasuk kabar dari kakek dan ayah saya. Entah ini benar atau kabar burung, saya tidak tahu.
Kaba burung paling menarik, saat raja menuntaskan pademi kolera di sebelah timur Desa Satra. Sudah beberapa hari kematian menjemput masyarakat desa di sana. Tetua desa lalu menghadap raja di Puri Klungkung. Bendesa ini nyaris kena marah, karena terlambat melaporkan keadaan. Tindakan emergensi begitu cepat dilakukan sang raja. Jro Bendesa disuruh pulang duluan.
Tepat bajeg surya, sang raja sudah berdiri di depan Pura Prajapati desa bersangkutan, diiring seorang abdi sembari membawa pacanangan (tempat sirih). Lagi-lagi sang raja hanya memohon pendek di hadapan Palinggih Prajapati. "Mbok usanang pamitanga wadwan titiang, benjang i mbok jagi sungsut, ten wenten malih sane ngaturang canang tuh (Mbok hentikan, jangan lagi diambil rakyat saya, supaya besok mbok tidak bersedih, tidak ada lagi yang bisa menghaturkan canang kering)." Itulah permohonan pendek sang raja saat itu, entah itu jalan klenik atau jalan ilmiah, lagi-lagi saya tidak tahu. Grubug akhirnya menghilang.
Jalan selalu ada sesuai zamannya. Kita tahu konsep raja ala Jawa dan Bali adalah raja bagi semesta. Pengedali energi, raja bagi penguasa gaib, pengendali buta-buti, gamang, dan memedi. Siapa saja membaca sedikit karya-karya sejarah Prof C.C Berg, Soemarsaid Moertono, Slamet Muljana, akan memperoleh pandangan bagaimana kekuaatan mistis itu selalu melekat pada sang raja.
Selalu ada jalan memang, Kerajaan Airlangga misalnya; diselamatkan kesaktian Mpu Bharadah -- manakala kerajaan itu kolap termakan sihir Calonarang. Kita memang sedang menunggu keajaiban itu, seperti Airlangga menunggu Bharadah, pendiri "Universitas" Lemah Tulis itu.
Yang pasti Tuhan selalu hadir di tangan-tangan orang baik, di tangan pemimpin yang tetap merawat rasa olas asih. Di tangan dokter cerdas yang paham menuntaskan penyakit, di tangan politikus yang peduli pada penderitaan rakyat, di tangan terpelajar yang memberi arahan yang benar. Rahayu.
Wayan Westa
Pekerja Kebudayaan
//Jauh sebelum kapitalisme menguasai tanah Bali, sang wiku, Ida Pedanda Made Sidemen telah berhitung prinsip, membalik arus kesadaran, dari fenomena fisik geografis (karang-sawah) ke fenomena psikis jagad diri (karang awak)//
Senyap dan lengang. Itulah kesan pertama memasuki Geria Taman Sari, Sanur. Tak terlihat balai megah berukir, pun tak tampak mrajan mentereng didapuk prada emas. Hanya loji tua nyaris tak terawat - di mana ratusan rontal kini tersimpan. Ruangan loji sedikit pengap, buram dan gelap - sinar matahari tak cukup menembusnya. Sang penghuni, Ida Pedanda Made Sidemen, pendeta dan pengarang besar Bali abad ke- 21 telah berpulang, meninggalkan geria ini 20 tahun silam. Namun sejarah tetap mengenangnya. Sang pelaku utuh karma kanda dan jnana kanda ini ibarat fajar zaman - guru jagat tak terlupakan – sosok yang sanggup menyatupadukan kerja, pengetahuan, dan bakti jadi ketunggalan total - utuh menyeluruh jadi puja kehadapan Sang Mahakerja.
Datang ke geria ini setelah 20 tahun sang pendeta berpulang, terasa ada semangat tetap bisa diteladani kini – kendati sayup dan lamat, toh jejak sang pendeta masih bisa disentuh. Saat memasuki halaman mrajan yang tak seberapa luas itu - kesederhanaan tiba-tiba menyajikan sesuatu yang indah. Orang lalu dibuat tercenung, betapa di pengujung zaman kini, peradaban masa lalu itu kian menjauh, silam dan nyaris tak terjamah. Di sini “teks” hidup jadi lebih otentik tinimbang aksara dalam keropak. Karena jejak tulisan saat dituturkan ulang sungguh mudah membias. Bahkan tak jarang jadi kultus. Dan teks otentik itu kini telah menjadi milik masa silam. Mungkin juga milik dunia lain. Ia tak lagi menjadi teks hidup. Sementara ratusan teks yang kini terpejam beku di ruang loji tak mudah lagi dibaca. Ibarat mumi yang dingin. Hanya orang yang mengantongi “sim peradaban aksara” bisa “berdialog” dengannya. Agak tragis, memang. Walau, diam-diam teks yang tak bicara itu, telah melahirkan puluhan sarjana. Maklum begitulah kecenderungan teks tua mengalir kini, yang cuma jadi kajian akademis, kering dan nyaris terasa hambar.
Tercenung di halaman merajan, sembari memandang patung Ida Pedanda Made tengah duduk bersila – menatap dingin tanpa ekspresi. Orang segera diyakinkan bahwa, betapa kesederhanaan tidak mudah diwujudkan dalam kata-kata. Dan Ida Pedanda Made jelas tidak mewujudkan kesederhanaan itu dengan kata-kata. Patung Ida Pedanda Made karya sang murid, Ida Bagus Alit Pidada yang kini disucikan di pamerajan Geria Taman, seperti tak hendak menghapus ingatan zaman – bahwa Ida Pedanda sejatinya adalah seorang yogi, wiku yang senantiasa merealiasikan dirinya dengan kerja. Hanya dengan kerja kaki Tuhan kuasa disentuh. Kemandirian menjadi kunci hidup paling hakiki. Kemandirian mendorong orang menemu maharddhika.
Ada jejak tak bisa dilupakan saban memasuki merajan Geria Taman. Di tempat inilah Ida Pedanda Made menghabiskan hari tuanya – sebelum akhirnya dewa kematian menjemput. Amben di belakang bale piyasan tempat sehari-hari sang wiku beristirahat masih teronggok utuh. Ukurannya kira-kira 2 x 1,5 meter, beratap genting, terserung gedek nyaris lapuk. Di amben inilah Ida Pedanda saban hari berbaring, berbantalkan kayu gelondongan – tanpa baju, tak hirau hari hujan dan panas. Subuh, sebelum kokok ayam pertama bertalu menyapa pagi, Ida Pendada kerap terbangun, tidur terasa dicukupkan. Kesenyapan tiba-tiba pecah, manakala sang pendeta membangunkan abdinya I Tekek – lalu bersama-sama mengalunkan bait-bait Kakawin Ramayana. Sesekali dengan cermat Ida Pedanda memperbaiki terjemahan I Tekek yang salah. “Inilah kegemaran saban subuh dilakukan Ida Pedanda”, terang Ida Bagus Dupem, cicit angkat sang wiku yang kini merawat seluruh tinggalan “rohani” di Geria Taman.
Sayang, di pagi buta, dalam usia 126 tahun, tepatnya tanggal 10 September 1984, tepat di purnama kapat, suara parau yang kerap memecah sunyi subuh itu tidak terdengar lagi. Pagi betul-betul jadi senyap, bait-bait Kakawin Ramayana tak terdengar dilantunkan kembali. Dewa ajal telah menjemput pendeta tua ini. Hanya sang abdi bernama I Tekek duduk merunduk di samping jenazah. Di pagi indah itu, saat bunga-bunga mekar, Ida Pedanda berpulang buat selamanya. Kesedihan menggelayut di bubungan merajan. Deburan ombak di Pantai Sanur masih nyaring terdengar- seperti menyambut roh Ida Pedanda. Pokok naga sari yang tumbuh dekat sumur merajan tiba-tiba meluruh. Teringat hari-hari saat sang pendeta masih bugar - sang kawi wiku (pendeta pengarang) kerap datang memetiknya, menyuntingkannya di telinga sesaat usai memuja Siwa Raditya, sang mahaenergi.
Namun di pagi itu pokok bunga naga sari seperti gelisah, tak sabar menunggu datangnya seorang taruna. Sayang sang taruna tak pernah kembali lagi. Sang pujaan keburu menghadap dewa keindahan, kekasihnya yang abadi. Sejarah hidup Ida Pedanda Made Sidemen pun ditutup dipengujung pagi. Ia pergi setelah mempersiapkan seluruh sarana upakara kematiannya.

Tentu banyak orang merasa kehilangan manakala Ida Pedanda pamit dari dunia ini. Menghadapi tokoh ini tak ubahnya menyelam di samudera luas. Sosok yang dalam hidupnya terakumulasi sejumlah peran dan kwalitas. Seorang wiku, pengarang, ahli arsitektur tradisional Bali, dan ahli pembuat tapel, walatanda. Justru itu tak berlebihan bila Ir. Robi Sularto, arsitek senior yang dikenal dekat dengan beliau memuji Ida Pendanda sebagai ilmuwan terakhir abad tradisional. Seorang pandita yang telah memecahkan arsitektur tradisional Bali secara komperehensif, seorang ilmuwan Timur yang komplit”. Sementara Antropolog Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus (almarhum) menyatakan, “Dia mengingatkan saya kepada ahli pikir India abad ke- 8, Sankara, yang melaksanakan agama melalui ilmu pengetahuan. Dia adalah ilmuwan Bali terbesar yang saya kenal. Orang suci yang mengabdikan segenap kemampuannya bagi kebajikan masyarakat”.
Dilahirkan dari keluarga Brahmana pada hari Selasa Wage, Wuku Dungulan, Saka 1800 atau 1878 M di Geria Taman Sari, Sanur. Semasih welaka, saat mana belum didiksa, disucikan jadi pendeta, Ida Pedanda Made bernama Ida Ketut Aseman. Menginjak taruna ia menyunting Ida Ayu Rai dari Geria Sindu, Sanur. Sayang bahtera rumah tangga tidak bisa diteruskan, karena sang istri menolak menjalani hidup sebagai wiku, di mana dalam usia muda harus menjalani upacara diksa. Pedanda Made pun memberi kebebasan Ida Ayu Rai. Bahtera rumah tangga tak bisa dipertahankan. Ida Ketut Aseman mengambil sikap berpisah. Dari perkawinan ini beliau melahirkan seorang putri bernama Ida Ayu Pidin. Selang bebarapa lama, Ida Ketut Aseman menyunting istri kedua, setelah madiksa bernama Pedanda Istri Made, dari Geria Puseh, Sanur. Dari perkawinan kedua ini lahir seorang putri bernama Ida Ayu Siti.
Merasa diri sebagai orang yang menambah padatnya penduduk (pangresek jagat), tidak berguna miskin dan malas, yang hanya bisa bicara, bagai suara burung di pagi hari. Menginjak usia 27 tahun Ida Ketut Aseman pergi meninggalkan orangtua (maninggalin yayah bibi). Bersama kekasih hati, mengembara menyusuri desa-desa. Kegelapan seakan menyelimuti hati, akhirnya Ida Aseman menetapkan pikiran: hendak berguru menghadap sang nabe di Geria Mandara, Sidemen, Karangasem.
Bersama istri yang setia, Ida Ketut Aseman kukuh menentukan sikap. Ia hendak mengembara ke peradaban batin. Pilihan itu dinyatakan pada sang istri dengan penuh kesungguhan: “idep beliné mangkin makinkin mayasa lacur, tong ngelah karang sawah, karang awaké tandurin, guna dusu né kanggo ring désa-désa . Keinginan kakanda kini, coba melepas keterikatan dunia, tiada punya tanah sawah, hendaknya badan ini ditanami, dengan keterampilan hidup, sebagaimana panggilan orang-orang desa itu.” Inilah kunci kemandirian Ida Pedanda Made. Bahwa titik pusat kreatifitas, tidaklah terletak pada hal-hal fisik. Semestinya sumber diri itulah sepatutnya diberdayakan, dibor guna melahirkan generasi mandiri. Dari “tanah” yang terhampar di pusat diri ini seyogyanya diri ditanami kecerdasan dan keterampilan. Hanya dengan semangat seperti itu orang bisa mandiri, merdeka dalam menentukan diri sendiri.
Tak terpeleset, memang. Nyatanya, penghayatan pada “guna dusun” itu mengantarkan Ida Ketut Aseman tak cuma menjadi seorang pendeta besar. Namun sekaligus juga seorang petani yang saban hari memuja ibu bumi dengan tambah, menerjemahkan puja dengan kerja. Lalu kian hari tumbuh menjadi seorang arsitek yang paham filosofi rancang bangun, pasih dalam ilmu mengukur tanah, menguasai keterampilan hidup begitu luas: menakik tapel, mengukir arca pralingga, membuat kulkul [kentongan], pemulas warna, sekaligus pengarang besar yang dihormati - perancang candi bahasa ternama. Atas pilihan hidup itu, ratusan teks keagamaan disalin ulang, puluhan karya satra diciptakan.
Sebagai ahli sastra - sebagaimana tersurat dalam cacatan otobiografis geguritan Salampah Laku, terang dicatatkan bahwa, Ida Ketut Aseman pertama kali belajar sastra dari Ida Bagus Jelantik di Geria Somawati. Begini antara lain Ida Pedanda menuliskan semangatnya: Sun anut solahing guru, sang wonten ring Somawati, juru kawi Bali kuna, pratama guru mangaji, maguru lagu len tembang, nama Ida Bagus Jelantik [Saya mengikuti jejak guru, berumah di Somawati, pengarang Bali Kuna, pertama belajar pada guru, mendalami lagu dan tembang, Ida Bagus Jelantik nama beliau. Namun bersama-sama dengan I Gusti Made Agung, Raja Badung yang gugur dalam perang puputan, Ida Aseman juga belajar sastra pada seorang pendeta dari Geria Sindu, Sanur. Sudah tentu pembelajaran bertahun-tahun di Geria Sidemen dan Budakeling, Karangasem merupakan pembelajaran panjang - kelak membentuk prototipe-nya sebagai pendeta besar.
Sementara keterampilan menakik tapel beliau pelajari dari seorang guru di Puri Gerenceng, Denpasar. Bakat beliau dibidang sastra diterima dari garis ayah. Sementara bakat arsitektur diterimanya dari garis ibu. Maka jadilah Ida Pedanda Sidemen pengabdi hidup di jalan kerja dan pengetahuan. Melakoni hidup di jalur kreatifitas religius disebut sebagai bhasma sesa dan gandha sesa. Bhasma sesa adalah jalan pengetahuan mengikuti jejak Bhagawan Byasa. Sedangkan gandha sesa, merupakan kreatifitas kearsitekturan, guna gina Bali mengikuti jejak Bhagawan Wiswakarma. Inilah ketunggalan kerja yang komplit, utuh menyeluruh. Suatu sikap dan pilihan di mana kelak membentuk diri jadi kreatif dan inovatif - mandiri dan merdeka. Pendeknya, pilihan itu ditransformasikan ke bidang kehidupan lebih luas. Di situ ilmu tak jadi keramat, ia teraplikasi penuh dalam hidup sehari-hari.
Memasuki usia paro baya beliau mengaku baru berguru dua kali. Dan sang calon pendeta berkeinginan kembali ke Mandaragiri (makasudnya Geria Mandara, Sidemen) menghadap sang guru - untuk berguru buat ketigakalinya. Mangungsi Mandari Giri, puput maguru ping telu, malih amari wara, ngusap suku sang resi, gawe ayu dadi jejek sang pandita [Menuju Mandara Giri, setelah tiga kali berguru, kembali memohon pensucian, mengusap kaki sang rsi, jalan mulia menjadi pendeta].
Demikianlah, di pagi buta, Ida Ketut Aseman berangkat di pagi hari ditemani sang istri menyusuri pantai selatan Pulau Bali. Setiba di Mandara, sang pandita guru menerima Ida Aseman sebagai murid paling bungsu. Seterusnya melewati proses diksa (disucikan) Ida Ketut Aseman berganti nama menjadi Ida Pedanda Made Sidemen.
Dua puluh tahun Ida Pedanda Made Sidemen telah berpulang. Namun di tengah-tengah dunia yang tengah sakit ini ada hal penting senantiasa perlu dicamkan dari sikap hidup Ida Pedanda Made. Dalam arus zaman yang kian memadat, jauh sebelum kapitalisme menguasai tanah Bali, bukankah sang wiku telah berhitung prinsip? Membalik arus kesadaran, dari fenomena fisik geografis (karang-sawah) ke fenomena psikis jagad diri (karang awake tandurin). Bahwa badan manusia Bali-lah sesungguhnya tanah yang paling menentukan masa depan Bali. Untuk itu pilihan pencerdasan, pembelajaran diri, mengasah “guna dusun” dalam konteks modern menjadi komitmen penting strategi Bali masa depan. Sebab, badan inilah benteng terakhir manakala gelombang globalisasi merambah “tanah” dan “natah” Bali.
Iya, pendeta yang memilih jalan sunyi sejak usia muda itu memang telah pergi meninggalkan jazadnya, tapi ajarannya, pesan-pesanya masih bisa kita simak dalam guratan-guratan lontar yang bertumpuk, pesan itu mesti dialirkan, ke kanal-kanal baru, ke telaga-telaga jiwa peradaban batin Bali. Ketika kanal peradaban mulai keruh, saat agama, upacara, ilmu tak kuasa memberi nyala hidup kembali, yang silam tak mesti ditinggalkan, yang lampau harus hadir dengan kesegaran baru. Yang silam harus hadir mengisi nutrisi jiwa yang baru, maka senantiasa peradaban batin itu menyala, bagai gni sakunang, nyala yang menyejukkan. ***
Catatan: Pendeta ini lebar 10 -9-1984
I Wayan Westa,
penulis, pekerja kebudayaan
Jauh dari kesan menonjokan diri. Polos dan sederhana. Bicaranya pelan, sedikit terbata, tampak hati-hati mengutarakan pendapat, sedikit dingin menghadapi pandangan berbeda. Dialah Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudharta MA, guru besar bahasa Sansekerta Fakultas Sastra Universitas Udayana. Usianya mengingjak 70 tahun saat saya melakukan wawancara di tahuh 2005.
Usia panjang plus kesehatan prima betul-betul jadi berkah, memang. Ini mungkin anugerah atas kesabaran dan kesederhanaannya. Walau bertahun-tahun menghuni Gedung MPR, menjadi wakil rakyat, Pak Tjok -- begitu ia kerap disapa para kolega dan mahasiswanya -- sama sekali tidak menunjukkan seorang agitator politik penuh nafsu. Sosoknya tetap seorang guru santun, agamawan, ahli Sansekerta, dan penulis buku yang rajin. Ada puluhan buku ia tulis, sejumlah terjemahan, serta ratusan makalah. Kitab Manu Smerti adalah buah terjemaham Pak Tjok bersama kolega Bapak Gede Puja.
Bila tidak ada aral melintang, pertengahan tahun ini pria yang pernah menjadi asisten dosen ahli Jawa Kuna, Prof Dr Poerbatjoroko di Universitas Gajah Mada periode 1958-1951 ini akan mengucapkan pidato purna tugas -- mengakhiri masa aktif sebagai guru besar Sansekerta yang langka itu.
Lahir di Puri Amertasari, Ubud, Gianyar, tanggal 24 Juli 1935, sang ayah bernama Tjokorda Gde Ngurah Sudharta, pegawai tata usaha di zaman punggawa Ubud, Tjokorda Gde Raka Sukawati. Sang ibu, Ni Gusti Putu Rai, seumur-umur cuma sebagai ibu rumah tangga, mengurus, mendidik dan membesarkan anak-anak.
Nasib bapak empat anak ini tiba-tiba jadi terlunta manakala sang ayah Tjokorda Ngurah Sudharta mengalami kebutaan total. Saat sang ibu mengandung anak pertama, sang ayah didera sakit mata. Seorang dukun mengobatinya dengan air kunyit warangan (kunir yang berwarna kemerah-merahan). Namun lacur, entah sengaja atau tidak air kunir obat mata itu tercampur larutan belerang. Begitu diteteskan di mata, kontan indra utama sang ayah hancur, perih tak tertanggungkan.

Nasib buruk tak bisa dihindari, maka jadilah sang ayah seorang buta seumur hidup. "Sejak awal ayah tak pernah mengenal rupa anak-anaknya. Beliau hanya mengenal suara kami, jeritan kami, dan rengekan kami." Tapi syukur kala itu ayah tergolong sangat terpelajar, wawasannya luas, teman-teman beliau sering menjulukinya sebagai kamus berjalan," kenang kakek dua cucu ini.
"Kami tumbuh besar dan dididik dari seorang ayah yang buta. Walaupun kami hidup di lingkungan puri, hidup kami tergolong pas-pasan. Saya tumbuh jadi anak bandel, hingga keluarga, saudara memanggil kami "Tjok Tengil", artinya: Tjokorda Bandel, " papar penulis sejumlah buku agama ini.
Menginjak usia tujuh tahun, belia Tjokorda Rai mulai mengenal pendidikan sekolah desa. Saat itu Ubud belumlah merupakan desa dunia, satu destinasi dimana para turis sejagat menyemut datang ke Ubud, melihat alam desa yang asri, kesenian dan kebudayaan yang memukau. Ketika itu yang ada di Ubud hanya sawah-sawah, jurang dan tebing yang indah, sungai-sungai berair jernih, pengembala bebek di pematang, kaki-kaki telanjang para petani. Gamelan, tarian, lukisan memang telah menjadi keseharian masyarakat Ubud kala itu, telah menjadi bagian utuh kehidupan masyarakat Ubud. Namun semua itu dilakukan semata-mata panggilan dewa-dewa saat odalan di Pura. "Itulah bagian terpenting persembahan kami, dalam aneka ragam upacara. Ini adalah ruang hidup kami, tempat kami belajar iklhas sembari merawat dan mengalirkan kebudayaan. Musik, tarian, lukisan, dan odalan selain sebagai persembahan, juga menjadi hiburan jiwa-jiwa kami, inilah yang menjadi nyala hidup kami di Ubud," urai Tjokorda Rai.
"Saya menyadari, dalam lingkungan seperti inilah kami bertumbuh, mengalir alami, hingga suatu saat mengantarkan saya meretas batas-batas dunia. Saya sekolah ke India, mengunjungi sejumah negara, menyadari, membaca kebudayaan mereka. Tapi, setinggi-tinggi kami meraih dunia, kami tetap orang Ubud, manusia Bali yang menyadari arti menjadi Bali -- anak-anak dari seorang ayah yang ditakdirkan buta. Kami merasa, betapa rindunya ayah melihat anak-anak, mungkin juga melihat cucu-cucunya."
Saat duduk di Sekolah Rakyat, Tjokorda Rai sangat gandrung menonton pertunjukkan wayang. Dari sinilah hidup lebih tinggi itu dimulai. Saban ada pertunjukan wayang ia senantiasa duduk di muka, melongok di depan kelir dengan perasaan tergugah. "Entah kenapa saya begitu tergila-gila wayang? Entah kenapa saya begitu keranjingan tokoh Anoman." Hingga saban nonton Anoman ia kerap merasakan dirinya sebagai Anoman, sebagaimana ia baca kemudian dalam epos besar Ramayana.
Demikianlah gara-gara dirasuk adegan Anoman, di masa kanak-kanak Rai Sudharta sering melakukan adegan-adegan yang berbahaya, naik ke pohon-pohon sembari melompat-lompat seperti Anoman. Kelakuan ini kerap membuat sang ibu marah-marah. "Sungguh sangat sering saya dijewer ibu, lalu esok hal yang sama saya ulangi juga, itulah kenapa kemudian saya dipanggi si tengil. Karena untuk urusan "kerangsukan" tokoh Anoman, saya melawan nasihat ibu. Sedih bila diingat," kenang Tjokorda Rai menerawang masa kanak-kanaknya.
Karena kelewat nakal, begitu naik kelas empat Sekolah Desa, Tjok Rai dipindah ke Singaraja, numpang di rumah keluarga dekat. Baru kemudian ketika naik kelas enam ia kembali ke Ubud. Sebagai anak sekolah Tjok Rai tidak menunjukkan bakat istimewa. Nilai raportnya biasa-biasa saja. Tamat Sekeloh Desa tahun 1945, Tjokorda Rai kembali ngendon ke Tanah Panji Sakti, Singaraja, guna melanjutkan ke sekolah menengah di SMP Baktiyasa. Secara kebetluan tempat tinggalnya sangat dekat dengan rumah pengarang Indonesia I Gusti Panji Tisna, dan tak jauh pula dengan "rumah lontar" Gedong Kirtya.
Saban senggang di usia masih tergolong remaja Tjokorda Rai tergelitik melancong ke Gedong Kirtya, saban ada waktu ia selalu ke sana, membaca majalah-majalah berbahasa Melayu -- hingga suatu hari kala sekolah SMA di Singaraja ia sempat mengabdikan tenaganya untuk mencatat nama-nama rontal yang terkumpul di Gedong Kirtya. Tanpa disadari dari sinilah hidup Tjokorda Rai mulai berkelok, ia tertarik membaca naskah-naskah lama, sembari sambil lalu belajar bahasa Kawi. Memang minat belajar bahasa Kawi mulai tumbuh saat sekolah di SMA di Singaraja tahun 1951. Dan anak muda ini lalu kian rajin bergumul di Gedong Kirtya, belajar pada guru-guru otodidak disitu-- membaca naskah-naskah lama secara pelan. Ia sadar bahwa di lontar-lontar itu tersimpan peradaban batin manusia Bali, sumber pengetahuan yang melimpah. Karenanya ia pun jadi kian tertarik, ada banyak hal yang perlu digali serius. Membacanya seperti menimba sumur yang tak pernah kering.
Kebetulan di saat SMA di Singaraja ia bertemu I Gusti Ketut Ranuh, guru bahasa Jawa Kuna yang amat telaten, dikagumi murid-murid karena pandai bercerita dengan pesan amat mendalam. Dari sang guru ini Tjokorda Rai muda banyak menimba ilmu, belajar tata bahasa Kawi dengan penuh gairah. Tapi diantara guru-guru yang ditemui di Singaraja, ia terkesan dengan penampilan Dr. R. Goris, ahli Sansekerta berkebangsaan Belanda. Goris-lah orang pertama yang mengajarkan Tjokorda Rai tentang dasar-dasar bahasa Sansekerta. Entah kenapa ia dibuat terkesima pada bahasa yang satu ini. "Mungkin karena kepintaran Goris mengajar," ungkapnya pada suatu hari. Minatnya kian menggelembung pada studi Sanssekerta ketika ia bertemu Prof. Dr. Raghu Vira, ahli Sansekerta asal India, yang saat itu tengah melakukan studi pada naskah-naskah Bali.
Raghu Wira-lah yang melecut Tjokorda Rai supaya mau studi ke India, memperdalam bahasa Sansekerta. Hingga saat ini ia masih terkenang kata-kata sang profesor itu, "Tjokorda, kau harus studi ke India, belajar Sansekerta, biar saya urus beasiswamu. Semua keperluan untuk berangkat belajar ke India saya yang menangani." Namun kala itu Tjokorda Rai sedikit ragu. Begitulah tamat SMA di Singaraja tahun 1954, ia mesti pulang dulu ke Ubud, mohon izin dan restu pada sang ayah.
Untungnya sang ayah sangat terbuka, yang kendati buta, paham zaman tengah bergerak, lalu membiarkan sang anak menuruti pilihannya. Terkenang nasihat singkat sang ayah, "Rai, Aji (ayah) tidak punya apa-apa buat bekalmu ke India. Berangkatlah bila memang ada yang membantu! Bekal Aji cuma satu: ingat itu ta-ju-din!"
Apa itu "ta-ju-din" Aji? Tanya Tjokorda Rai sedikit was-was.
"Camkan dalam hati, "perintah sang ayah.
"Ta-ju-din" itu artinya; taat, jujur, dan rajin. Kemana pun kau mengembara dengan bekal ini pasti berhasil. "Aji ingat kata-kata pendeta dari Sanur, Ida Pedanda Made Sidemen. "Bila engkau tidak punya tegal sawah, tegal dalam dirimu itulah hendaknya kau tanami ilmu pengetahuan. Pupuk dengan kerajinan dan amal," papar Tjokorda Rai Sudharta mengenang pesan sang ayah.
Kendati telah mendapat izin keluarga, pria yang pernah menjadi korespenden Majalah Panca (Yogyakarta) dan Majalah Damai (Denpasar) ini tetap ragu untuk berangkat. Ia sedikit pangling mengingat nilai bahasa Inggirsnya cuma enam. Ini jelas tak memenuhi syarat. Pengajara bahasa Inggrisnya saat itu adalah Ibu Gedong Bagoes Oka. Dengan perasaan malu dan hati tertekan ia coba menghadap Ibu Gedong.
"Ibu apakah saya boleh berangkat studi ke India? Ibu Gedong cuma menjawab pendek, "Berangkatlah."
Demikianlah di tahun 1954, dengan cuma mengantongi nilai bahasa Inggris enam Tjokorda Rai berangkat ke India. Di sana, di Internasional Academy of Indian Culture, di bawah bimbingan langsung Prof. Dr. Raghu Vira.
Tahun 1955- 1957 ia kuliah di Banares Hindu University sampai mendapat gelar BA. Kemudian pulang kembali ke Indonesia menjadi asisten dosen Prof Dr R. Ng. Poerbatjaraka di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, mengajar mata kuliah bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna.
Belum genap setahun menjadi asisten dosen, Pak Poerba menanyakan titel akademisnya.
"Tjokorda titelmu apa?"
"Cuma BA Pak," jawabnya lugu.
"Wah , BA itu artinya: belum apa-apa. Kamu balik lagi ke India," perintah Pak Poerba dengan wajah dingin.
Tahun 1958-1961, atas beasiswa negara, Tjokorda Rai Sudharta balik lagi ke India guna melanjutkan studi di Punjab University, New Delhi hingga memperoleh gelar MA. Karena belum dipanggil pulang ke Indonesia, ia bekerja sebagai Atase Kebudayaan di Kedutaan Besar RI, New Delhi. Kala itu di KBRI, atas prakarsa Atase Kebudayaan RI bekerja sama denga Atase Kebudayaan negara- negara sahabat, Tjokorda Rai sempat meraih juara II lomba mengarang berbahasa Inggris, mengalahkan peserta dari Australia, Amerika dan negara-negara sahabat lainnya. "Beh nika uilian jengah maan nilai bahasa Inggri aji nem," kenang doktor Sansekerta jebolan Universitas Indonesia ini.
Memasuki pertengahan tahun 1962, setelah menyandang gelar MA, Tjokorda Rai kembali pulang ke Indonesia. Ia hendak memenuhi janji Prof. Dr. Poerbotjoroko yang saat itu masih mengajar Kesusastraan Jawa Kuna di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Pulang dari India, Tjokorda Rai langsung menghadap Pak Poerbo. Begitu menghadap, sang asisnten langsung dihardik, "Lho Tjokorda, ngapain balik ke sini, pulang saja ke Bali, di sana saya sudah bangun Fakultas Sastra. Engkau mengajar saja di sana," demikian Tjokorda Rai menirukan instruksi sang mentor Poerbotjoroko.
Dan sejak tahun 1962 Tjokorda Rai pun diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Universitas Udayana, sebagai fakultas paling tua di Bali.
Setahun mengajar di Udayana, terhitung dari tahun 1963-1969 Tjokorda Rai kemudian diangkat menjadi Kepala Jawatan Agama Provinsi Bali, sementara dalam waktu yang sama menjadi dekan pertama Fakultas Agama dan Kebudayaan Institut Hindu Dharma (Unhi sekarang), Denpasar. Jabatan ini ditinggal karena di tahun 1967-1969 ia ditunjuk sebagai anggota Badan Pekerja MPRS. Setelah nantinya ditunjuk sebagai anggota DPRGR. Lantas di tahun 1971-1987 diangkat menjadi anggota DPR RI. Sempat keliling Eropa dan Asia melakukan survei perihal tanggapan agama-agama terhadap family planning (keluarga berencana) -- sebelum akhirnya mulai Oktober 1987 ia kembali mengajar di Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Di tengah-tengah kesibukan mengajar dan menjadi anggota legislatif, Tjokorda Rai juga diikutkan sebagai anggota tim menerjemah kitab-kitab suci Hindu di Departemen Agama RI. Demikian, bersama almarhun Gde Puja SH, ia menerjemahkan kita Manu Smerti, Compendium Hukum Hindu. Di samping menulis sejumlah buku-buku Hindu atas "perintah" Prof. Dr Ida Bagus Mantra . Sementara di sela-sela waktu mengajar dan kesibukan yang seabreg itu Tjokorda Rai menerjemahkan The Call of The Upanisad -- yang belakangan diterbitkan Majalah Gumi Bali SARAD atas saran saya sendiri. Buku ini terbit dengan judul Panggilan Upanisad, Bertemu Tuhan Dalam Diri (2007).
Sebagai ilmuwan dan pendidik Tjokorta Rai Sudharta memang tidak sempat membidani pendirian majelis keagamaan di Bali, tapi dibalik kelahiran Parisada ia merupakan satu diantara tiga tokoh ikut menggodok ide-ide itu sebelum Parisada didirikan, 23 Februari 1959. "Jauh sebelum Parisada didirikan, kami bertiga (Dr. Ida Bagus Made Mantra, Ida Bagus Punyatmaja, Tjokorda Rai Sudharta) sering berkumpul di India, kebetulan sempat sama-sama sebagai mahasiswa di sana. Pertemuan itu kerap atas prakarsa Pak Mantra. Kami berdiskusi sampai larut, membahas masa depan Agama Hindu di Bali," kenang Tjokorda Rai.
Tiga serangkai ini sadar, ketiga Bali terintegrasi penuh ke pangkuan Republik, Hindu nyaris tak punya pengayom tunggal. Dulu urusan agama berada di bawah kebijakan raja, tetapi ketika raja-raja tidak lagi memiliki kekuatan politik, urusan agama jadi tak karuan. Maka diperlukan sebuah lembaga pengayom di luar kekuatan negara. "Nah atas pertimbangan inilah Parisada didirikan. Dengan demikan Hindu memiliki payung tunggal, yang khusus mengatur tata agama dan kepentingan lain. Ya saat itu kami cuma berpikir lokal, semata berniat mengayomi kepentingan Hindu Bali," urai Tjokorda Rai Sudharta.
Menjelang memasuki purnatugas sebagai guru besar Sansekerta, di rumahnya yang tua, rumah yang ditempati lebih dari 40 tahun, di Jalan Serma Gede nomor 14, Denpasar, sang guru masih rajin mengirim sejumlah artikel agama ke Majalah Warta Hindu Dharma, majalah yang sejak awal turut dirintisnya bersama Dr. Ida Bagus Mantra, Drs. Ida Bagus Punyatmaja MA. Saban pulang ke Puri Amertasari, Ubud, Tjokorda Rai masih suka membuka-buka lontar tinggalan leluhurnya. Saban bulan ia masih setia menjawab pertanyaan-pertanya seputar tatwa untuk pembaca Majalah Gumi Bali SARAD.
"Wah saya tidak bisa mengetik dengan komputer. Setiap ngetik saya minta tolong kepada pegawai penerbit Upada Sastra, biasanya saya menyerahkan tulis tangan begitu saja," aku Tjokorda Rai sembari menyatakan dirinya ketinggalan tehnologi. Kerap, memang Pak Tjok mengirimkan jawaban rubrik konsultasi Tatwa SARAD dalam naskah tulis tangan. Dalam lembar-lembar jawaban itu Pak Tjok tampak bersungguh-sungguh, kata demi kata dikoreksi dengan jeli, kadang begitu rinci. Bahkan hanya untuk salah ketik saja, Pak Tjok sering menelpun redaksi berkali-kali.
Untuk urusan keilmuan pada bidang yang ia sangat cintai: sastra Sansekerta dan Jawa Kuna Pak Tjok mengaku amat beruntung; begitu banyak kebajikan dan nasihat yang ia dapatkan untuk menentramkan batin. Untuk sekadar diketaui, atas prakarsa Bapak Ida Bagus Mantra, Tjkorda Rai Sudartha-lah salah satu tim penulis buku Upadeca.
Upadeca disajikan dengan gaya bertutur. Bahasanya bening mengalir, hadir dengan percakapan didaktis antara Rsi Dharmakerti dengan muridnya Sang Suyasa. Orang boleh menangkap Sang Suyasa sebagai murid zaman, yang rindu menghadap guru agung Rsi Dharmakerti, lalu dengan sujud berkata, “Oh Guru suci, hamba datang mohon pengajaran , sudi terangi hamba dari kegelapan”. Dan tulisan-tulisan didaktis yang mengalir di buku Upedesa itu adalah gaya bertutur dari Tjokorda Rai Sudharta.
I Wayan Westa
Pekerja Kebudayaan
Catatan: profil singkat ini saya tulis di bulan Januari 2005, manakala Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudharta belum berpulang dimuat di Majalah Gumi Bali SARAD.
//Tuhan bagi manusia Bali adalah sesuatu yang menubuh, sangat dekat dengan hidup sehari-hari, maka Tuhan dipuja lewat sarana yang paling dekat pada hidup//
Tiada paling jahil tinimbang Pan Bungkling dalam urusan kesangsian ber-Tuhan. Dalam teks geguritan berbahasa Bali, sosok antagonis ini digambarkan sebagai kritikus tanpa tedeng aling-aling. Menyangsikan aturan agama, meledek upakara, mencetang petuah suci sang pendeta. Saban hari kerjanya cuma beradu argumen, mengunjungi orang pintar, berdebat filsafat, mengkritik cerdik pandai yang sok tahu urusan Tuhan. Karena keberanian itu ia sering kena marah. Bungkling dicaci sebagai anjing hina, yang kerjanya hanya menggongong.
Namun di balik “kepandiran” Pan Bungkling, sosok nakal ini bukanlah seorang ateis, yang mengumandangkan slogan “Tuhan telah mati” sebagaimana kotbah tokoh filsafat Barat, Nietzche pengarang Zarathustra. Sebaliknya Bungkling kerap mengkritik uraian-urain berbelit pendeta mata duitan, yang pura-pura tahu perihal surga dan neraka. Yang menganggap hidup ini lurus selurus-lurusnya, tanpa belokan dan tikunagan.
Suatu hari Bungkling menghadap Ida Gede Gangga Sura, pandeta ternama, ahli upacara termasyur. Dari keahlian ini sang pendeta mendatangkan rezeki berlimpah, maklum selain sebagai pendeta, Ida Gangga Sura juga penjual banten, plus pendarma wacana andal. Sang pendeta dikenal sangat terpelajar, paham rumus-rumus suci, terampil berdebat. Karena itu, Pan Bungkling hendak datang mengolok-olok, sekaligus mengujinya. Sembari menyembah taksim, ia datang menghadap Ida Gede Gangga Sura, mengabarkan sang ibu kandung meninggal kemarin sore. Bungkling datang ke geria hendak membeli sesajen pabersihan (pensucian) buat jenazah sang ibu. Dengan biaya hanya dua belas ribu, pendeta ahli upakara menyanggupi. “Di geria semua urusan jadi gampang, di sini banyak ahli banten, “ jawab Ida Gede Gangga Sura pendek.
Begitu sesajen usai , Bungkling mengamati teliti, semua detail banten diperhatikan. Bungkling merunduk, mendekat kehadapan Sang Pendeta, yang saat itu tengah sibuk di pamerajan. Tak lupa menghatur sembah, Bungkling bersapa hormat, “Hormat tuanku pendeta utama, saya telah melihat sesajen itu, hamba agak bingung, betapa beraneka sarana tergelar di atas talam, ada cermin, baja, minyak, bunga melur, umbi gadung. Itu saya tahu, ini memang sesajen penyucian, namun saya belum mengerti, apa gunanya semua itu sang pendeta?” tanya Pan Bungkling polos.
“Pertanyaanmu ada-ada saja Bungkling, bawalah uangmu ke sini, jangan berdebat," anjur sang pendeta dengan nada berat.
Sang pendeta berlagak menjelaskan, “Beginilah maknanya, ini tradisi dari zaman dahulu, kelak bila menjelma kembali, bunga melur akan menjadi taring, umbi gadung akan menjadi kulit, cermin sebagai mata yang cerlang, baja sebagai gigi, agar kelak dalam penjelmaan nanti semua sempurna," terang Ida Gangga Sura yakin.

Bungkling tertawa terbahak-bahak, “Sekarang hamba mengerti, namun hamba heran, hamba pernah meliat orang mengubur sapi, tak disertai upacara apa-apa. Tapi hamba lihat, tak seekorpun mata anak sapi yang baru lahir itu bermata kabur? Bagimana dengan putra sang pendeta, kok sebelah matanya picek, mungkinkah cerminnya kabur, kulitnya juga kasar, apa mungkin umbi gadung yang dipakai belum dikelupas? Sodokan Pang Bungkling ini menyebabkan Ida Gede Gangga Sura marah, meledak tak ubahnya magma gunung. Bungkling diusir dengan kasar. Sembari tetap ketawa, Bungkling melengos keluar tanpa pamit.
Selebihnya silakan pembaca budiman mengapresiasi kritik ini, dan tidak hanya kini, kritik model ini sudah muncul sejak zaman dulu. Bisa dipastikan, dulu kritik semacam ini hanya keluar dari bibir seorang pendeta, tidak manusia sampah seperti saya. Dan Geguritan Bungkling ditulis oleh seorang kawi dalang, bernama Ki Dalang Tangsub, nama bekennya Rangdi Langit [bang akasa]. Selain Geguritan Bungkling ada juga Geguritan Bongkling, bisa jadi yang ini karya seorang pendeta.
Di balik pertanyaan kritis, pengarang Bungkling sebenarnya hendak meluruskan, menjewer tokoh panutan yang merasa tahu jalan kesejatian, kendatipun sesungguhnya tak seorangpun bisa memberi kepastian, tak seorangpun paham kebenaran final. Bahwa kita semua adalah para pencari. Karena sesesungguhnya manusia yang sadar itu adalah para pemburu makna. Makna dan penghargaan pada hidup itu membuat orang selalu bisa bersyukur, menjauh dari keangkuhan-keangkuhan tidak perlu.
Apakah laku yang dijalani Ida Gangga Sura dalam Geguritan Pan Bungkling merupakan jalan tunggal? Jawabnya, jelas tidak. Karena jalan dan cara tak lebih dari sekadar bagaimana manusia mendekatkan diri pada Sang Penentu Hidup. Semua jalan menyadari kehadiran Sang Maha Urip syah adanya. Namun dalam tautan keragaman Hindu Bali – ketunggalan jalan, sama artinya dengan tidak ada pilihan. Karena itu tetua Bali sangat menghargai yang namanya keragaman, termasuk dalam urusan ber-Tuhan dan beragama. "Ngungsi pucak gunung marginin saha idep, menuju puncak gunung pilih dari mana kita suka," ini isyarat yang diberikan para tetua Bali. Nun jauh, Bagawadgita menunjukkan upaya yang sama. “Jalan manapun engkau tempuh, semua akan sampai kepada-Ku."
Orang Bali udik tentu belum pernah membaca kitab Bagawad Gita. Kendati demikian, praktiknya telah dilakoni sebelum kitab ini jadi bacaan wajib kalangan terpelajar. Pertanyaan kemudian, seperti apa visi Ketuhanan manusia Bali? Bagi masyarakat yang tak akrab dengan teks, dan bagi mereka yang tak pernah mengenyam pendidikan ala sekolahan, Tuhan tentu jadi lebih khusus dalam pemahaman dan penghayatan mereka. Umumnya mereka tidak mengenal Tuhan sebagaimana dibayangkan para yogin. Juga tak mengenal Tuhan sebagaimana digambarkan kitab-kitab Weda dan Upanisad. Lalu apakah dengan begitu mereka tidak ber-Tuhan? Sekali lagi jawabnya: Tidak. Jangan lupa, bahwa tradisi rontal-rontal Bali menggambarkan Tuhan dengan aneka atribut, aneka fungsi, lengkap dengan aneka pemujan. Tuhan di-nyasa-kan didalam aneka medium, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Sekelompok aksara suci yang disurat pendeta saat upacara pawintenan adalah laku me-nyasa-kan Tuhan di dalam tubuh. Begitu juga banten, selain sebagai medium menyalur energi magis, sebagai bahasa, banten adalah wujud persembahan.

Tuhan bagi manusia Bali kerap disebut Widhi, Suwung, Embang, Maha Urip, dan Kawi. Sebutan ini jelas bukan nama-nama Tuhan pijaman ala India, melainkan nama Tuhan asli Bali. Jadi menarik dicermati dari laku “ber-Tuhan” manusia Bali bukanlah prihal konsepnya yang tinggi dan abstrak. Melainkan dalam ukuran penghayatan, orang Bali adalah pemuja yang tulus, polos dan sederhana. Dalam kultur hidup orang Bali, beragama bukan berarti memiliki semata pengetahuan agama. Namun bagimana melakonkan agama dalam hidup, tidak melulu tekstual, teoritis apalagi. Untuk itu dalam urusan dekat dengan Tuhan merupakan urusan pribadi. Seorang sulinggih belum tentu mendapat “kredit” besar di mata Tuhan tinimbang seorang petani lugu. Petani polos yang pikiranya tidak pernah berpaling pada yang lain, kecuali memuja bumi dengan tambah, cangkul. Tak pernah mengeluh dalam kondisi panas dan hujan.
Justru itulah di Bali orang menemukan beragam penghayatan ber-Tuhan demikian kompleks, luas dan jelimet. Tapi sejatinya manusia Bali tergolong pemuja yang rendah hati, terbuka pada sesuatu yang memberi keselamatan, ketenteraman, dan kemudahan hidup. Maka tak perlu disalahkan, jika orang Bali juga “menyembah” di pohon besar, di jurang yang keramat, di batu besar, dan di tempat-tempat yang dianggap memiliki tuah. Sesungguhnya mereka bukan pemuja berhala, mereka mengakui, menghormati semua ciptaan. Mereka suka merendahkan egonya serendah rumput, karena dengan begitu ia seakan-akan menyembah kaki-Nya.
Saban ada rerainan orang Bali menghaturkan sesaji di tungku jalikan tempat memasak, gentong tempat air, pada alat-alat dapur, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Di sini Tuhan bagi manusia Bali adalah sesuatu yang menubuh, sangat dekat dengan hidup sehari-hari, sebab lewat alat-alat itu ia memperoleh kemurahan hidup-- maka itu Tuhan dipuja lewat sarana yang paling dekat pada hidup. Karena aspeknya bertalian dengan hal-hal yang bisa dibayangkan, nyata, berwujud dan menubuh, aspek ini dalam lontar-lontar Bali kemudian disebut sebagai Saguna Brahma - Tuhan yang bisa dibayangkan, dirasakan, sekaligus dekat dengan keseharian.
Tak demikian halnya dengan kaum terpelajar, pandita bijak yang dekat dengan teks, di sini Tuhan dihayati sebagai sesuatu yang tak berwujud. Karena para pandita memiliki abstraksi tinggi, maka Tuhan dibayanngkan sebagai Nirguna Brhama, Tuhan yang tak dapat didifinisikan, apalagi dipikirkan. Justru itu Tuhan tak dicari dengan sarana upacara semata, tapi dicari lewat retret khusus, yakni entah namanya meditasi, upawasa, yoga samadi, dll.

Teks-teks yang menjelaskan penjelajahan Tuhan menuju asfek nirguna brahman di Bali lumayan beragam. Mulai dari kitab tertua Bhuwana Kosa, Ganapati Tatwa, Wrhaspati Tattwa, Jñānasiddhanta, Tutur Kalepasan, Jñāna Tatwa, dan sebagainya. Teks ini menjadi acuan penting bagi kaum yang suntuk memasuki peradaban aksara. Boleh dibilang teks ini merupakan kitab “upanisad” ala Bali. Para pandita menyebutnya sebagai tutur kalepasan atau tutur kapatian. Karena yang dijelaskan dalam teks ini semata bagimana cara mati yang benar, cara meniada dengan sungguh.
Pendeknya susastra di Bali cuma memaparkan dua hal penting, yakni bagimana hidup dengan benar, dan bagimana cara mati dengan benar. Teks-teks tentang dua jalan ini, alih-alih teks yang menunjuk pada pembebasan (kelepasan) sungguhlah melimpah. Para penekun agama di jalan teks, amat sering memperdebatkannya, menulisnya secara berulang. Meyakini semua aporisme itu sebagai kebenaran tak dapat digugat.
Dan Pan Bungkling adalah sosok yang amat garang mengkritik aporisme itu. Siapa saja yang suka membaca Geguritan Pan Bungkling akan mendapat gambaran, lompatan-lompatan pernyataan yang menyangsikan setiap argumen yang saling berkelindan. Pengarang Geguritan Pan Bungkling sebenarnya tengah melakukan otokritik bagi mereka yang terpenjara teks. Seorang pejalan rohani sesungguhnya adalah mereka yang telah melampaui teks. Ia yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai teks. Itulah sastra paraga, sastra yang menubuh, di mana seluruh pikirannya, kata-katanya, tindakannya adalah teks yang menyalakan kesadaran para pencari nyala hidup- sudipa ring kulem. Sekaligus tidak kering pemaknaan, gersang penghayatan, dan kerontang dalam laku sehari-hari. Dia itulah patirtan jagat, tempat orang-orang menemukan kesejukan batin. Dia pula guru-loka, guru bagi dunia saat zaman terombang-ambing kehilangan panutan.
Tabik
IWayan Westa
Pekerja Kebudayaan
Maṅkānugraha saṅ hyan Iśwara sinémbahakén ikaṅ anāma Lubdhaka/
atyantéki meṅen-meṅnya tékap iṅ paramawara paweh hyan Iśwara/
tuștāmbéknya -n amiśra dewa tuwi tan papahi lawan awak Jagatguru/
maṅgeh kāraṇa niṅ samaṅkana sakéng brata Śiwarajani ndtan kalen//
Begitulah anugerah Hyang Siwa diterima Lubdhaka/ ia amat gembira menerima berkah utama itu/ hatinya senang bisa menyatu dengan Siwa, sementara dewa sekalipun tak sepadan dengan Siwa/ semua itu didapat setelah ia dengan tekun melaksanakan brata Siwarajani//
Ada kisah yang selalu menyita perhatian kita saat Sasih Kapitu tiba, kisah yang menggetarkan atas seorang pemburu bernama Lubdhaka. Beradab-abad silam, Mpu Tanakung, seorang pujangga Jawa tersohor mengabadikan kisah ini sebagai jalan pembebasan [mukta-ṅ kleśa siluṅluṅanya muliheṅ nirāśraya juga. Berharap bebas dari segala penderitaan, bekal pulang menuju pembebasan]
Lepas dari misi dan ideologi Siwaistis Hindu Jawa—kisah ini tampak menyita permenungan demikian dalam, dan hingga hari ini mendapat perhatian besar sebagai malam peleburan papa, yang lazim disebut ‘malam Siwa’ atau Siwaratri. Dan pemeluk Hindu Bali menyambut hari suci ini dengan penuh gairah, amat semarak.
Mpu Tanakung-lah yang membentuk momen penting ini— setidaknya setelah Hindu Majapahit membangun tata kehidupan baru pada keyakinan rakyat Bali. Tanakung yang hidup sezaman dengan raja Sri Adisuraprabawa dari era Majapahit akhir menampilkan kisah ini begitu dramatis, didaktis, sekaligus memesona. Dengan medium bahasa Jawa Kuna, Tanakung seperti membangun telaga baru bagi zaman yang kian suram saat itu.
Sebagaimana diyakini para penganut Siwa, barang siapa yang dengan sadar menggelar Brata Siwaratri dengan ketangguhan puncak, segala kepapaan akan dilebur menunju pembebasan puncak. ...sapapa nika śirna denikaṅ brata ginawe akennya.
Untuk capaian puncak ini, Tanakung tidak menghadirkan tokoh yang tangguh dalam yoga. Sebaliknya ia menghadirkan seorang memburu yang nyaris tidak pernah berbuat kebaikan, yang kerjanya hanya membunuh dan membunuh, pemburu pemakan daging.
Demikianlah, tepat di hari keempat belas paruh bulan gelap sasih Kapitu, disertai hujan gerimis, pagi-pagi sekali Lubdhaka pergi berburu. Memakai baju biru kehitam-hitaman, membawa serta tombak, busur, dan panah Lubdhaka pergi seorang diri.
Perjalanan demikian jauh ke arah timur laut, dinaungi mendung dan gerimis pagi Sasih Kapitu. Melewati taman, dataran, kahyangan, pertapaan, bihara, yang sangat menawan hati. Tegalan luas di kaki gunung, beraneka tanaman di lerengnya. Air terjun memesona. Bangunan-bangunan tampak asri, atap pondoknya diliputi kabut dan gerimis. Asap mengepul, menari-nari di udara hendak menyatu dengan langit. Di bawah terlihat pohon beringin nan rimbun, seonggok balai berdinding tempat orang berunding.

Di sebelah barat ada dataran tinggi dengan huma luas, kebun-kebun subur dengan tanaman teratur rapi, dikitari pohon kelapa tengah disaput kabut. Burung kuntul terbang terkelap-kelip di tengah awan, seakan-akan hilang ditelan mendung karena tidak lagi tampak. Terlihat pertapaan para pendeta, pintu gerbangnya tinggi dan tembok pagarnya lurus. Pohon tanjung, cempaka, banah, nagasari tengah berbunga harum.
Di tengah-tengah kabut dan musim hujan Sasih Kapitu, Lubdhaka menyaksikan pemandangan menyesakkan. Bangunan tinggi tempat pemujaan rusak berat. Cabang penyangga berbentuk supit urang runtuh tak ada yang memperhatikan, temboknya rebah. Bangunan di halaman roboh, dan jalanan sepi. Atapnya berjatuhan tak dihiraukan orang, tiangnya condong tak karuan. Tampak ukiran di tembok bagai gadis perawan menatap langit, sungguh memilukan hati. Seperti menuturkan sakit hati karena lama tak ada pujangga menghampiri.
Lewat tokoh Lubdhaka, Mpu Tanakung seakan mengabarkan tanda-tanda zaman, "keruntuhan" sebuah keyakinan, merosotnya semangat ketuhanan. Pelukisan ini dengan mudah dapat kita simak dari penggambaran buram yang memilukan dari Kakawin Siwaratrikalpa.
Dengan wirama Ragakusuma misalnya; Tanakung menggambarkan sebuah Pura yang tak lagi dihiraukan. Sebuah persada puncaknya yang tinggi ditumbuhi rerumputan. Bagian tengahnya retak ditumbuhi pohon prih, rerimbunan pohon menaungi, semua palinggih rusak dibelit pohon-pohon melata. Begitu banyak bangunan suci hancur, saluran airnya tersumbat, taman-tamannya tidak lagi terawat.
Apa yang kita baca saat Mpu Tanakung menghadirkan tanda-tanda zaman seperti itu? Apakah ini gambaran awal dari senja kala Majapahit, di mana masyarakat tak lagi hirau pada dewa, tempat sucinya dibiarkan tak terawat, di sana-sini yang terlihat cuma balai-balai dan prasada yang rubuh, sepi tak ada pengunjung. Atau Tanakung tengah menangkap masyarakat Majapahit berangsur pindah keyakinan? Atau, apakah Tanakung ingin menggenapi kecemerlangan Mpu Tantular yang menulis Kakawin Sutasoma bernapaskan Buddha? Kita tidak tahu semua ini.
Jika benar Kakawin Siwaratrikalpa ditulis di masa akhir Majapahit, gambaran buram itu tampak benar adanya. Dan karenanya Tanakung berusaha menghidupkan kembali semangat keagaamaan itu dengan menulis kakawin sembari memuliakan kesucian Siwa sebagai maha pelebur kepapaan. Di tengah-tengah kekeringan zaman yang senja, Tanakung seakan menjajikan surga masa depan. Dan betul, sampai detik ini, di tempat ini, di Pura Lokanatha yang indah kita masih mengorek-ngorek titipannya, mendiskusikan sepenuh gairah.
Bahwa, dalam keyakinan Siwaistis, pembebasan itu akan ditemukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang paling hina dina sekali pun. Bila Lubdhaka, orang yang paling papa akhirnya mendapat surga, yang tanpa sengaja melakukan brata Siwa di malam Siwa, ia pun akhirnya terbebas. Dewa-dewa menjemput rohnya saat kematian.
Bagi kita Tanakung telah melahirkan peradaban spiritual dengan magnitud besar, tradisi yang tak mudah lekang digerus zaman. Sekian abad setelah keruntuhan Majapahit, tradisi spiritual yang dilahirkannya hidup terus di benak para generasi. Namun tanda-tanda zaman yang digambarkan Tanakung setidaknya mesti dibaca kembali, demi membaca tanda-tanda hari ini-- karena toh betapa sering di zaman yang serba mudah, berlimpah, hidup dibuat sering lebih garing, dibekuk tamas kenikmatan-kenikmatan rendah. Dan manusia jadi lupa sang muasal.
Bila Tanakung menukilkan gambaran buram tentang tanda-tanda zaman yang rapuh, candi-candi roboh, tak ada mengunjung yang datang ke tempat suci, jalanan sunyi -- lalu apa yang mesti kita baca dari kesemarakan beragama di Bali? Pura-Pura kita megah, terawat dengan bagus, pamedek nyaris tak pernah sepi, busana kita amat bersih, wangi dan rapi, sembari menggengam ponsel tercanggih, lalu apakah ini tanda sebuah kebangkitan rohani? Sungguh sulit mengukur dengan parameter apapun, kecuali kita menjadi makin sadar dan bahagia, dan lagi-lagi, ini tak mudah dikur dengan hitungan statistik pula.
Tapi apapun itu, Tanakung tetap memberi harapan, malah sebagai pemuja Siwa ia memberi janji, bagi siapa pun yang melakukan brata Siwaratri dengan tekun, setidaknya ia mendapat 'pembersihan" jiwa, nun yang lebih utama tentulah pembebasan lahir batin. Karena di titik ini, Siwa seakan memberi pemenuhan, bahwa seorang papa pun akan terbebas dari segala belengu dunia. "tesam papani pasyanti Śiwaratri prajagarat," demikian disuratkan kitab Padmapurana.
Kitab Wrehaspatitattwa malah memberi realisasi amat terang bagaimana seorang papa bisa terbebas dari kepapaannya. Di situ dalam dialog Hyang Siwa pada Bhagawan Wrehaspati, realisasi itu dipaparkan begini: ....yan maturtur ikaṅ ātma ri jatinya, irika yaṅ alilang, sang ātma juga umidépa saka suka duka niṅ śarira. ..jika atma sadar tentang jati dirinya, di situ lenyap[segala kepapan], sang roh sadar akan suka-duka dibelengu tubuh.
Ada tiga brata inti wajib dilakukan dalam upacara Siwaratri. Tiga brata itu meliputi; Mona [diam, tidak berkata-kata], Upawasa [tidak makan minum], dan Jagra [tidak tidur dilakukan selama 36 jam, mulai dari pagi hari pada panglong ke-14 sampai pada senja hari panglong ke-15].
Sedangkan Mona dan Upawasa dilakukan selama 24 jam, mulai dari pagi hari panglong ke-14 hingga pagi hari panglong ke -15.
Bila pun ada tiga brata ini, dalam pandangan orang-orang suci, Jagra tetaplah menempati urutan paling utama. Sebab tanpa Jagra, dua brata lainnya tidak bisa dilakukan. Sampai pada titik ini, brata Siwaratri sesungguhnya adalah kepatuhan dan perjuangan melawan lupa. Siapa pun tengah dibelit lupa dipastikan dia berada dalam kondisi turu (tidur). Mereka yang senantisa tidur, atau tidak sadar, atau tan atutur. Dan bagi mereka yang tidak sadar, yang selalu tidur tidak mungkin terjadi kebangkitan kesadaran, alih-alih kebangkitan rohani. Kesucian [Siwa] tidak akan mendekat padanya.
Wayan Westa
Kusa Agra,
Tilem Kapitu,
20-1- 2015
Saya baru berkesempatan mendengar kembali Minatory saat Noerdy mengirimkan tautan videoklip "Intoleransi", respon pertama saya adalah "wow, they're still around, that's kool!" lalu bergegas menonton dan kaget dengan evolusi musik mereka; Intoleransi adalah lagu dengan riff berbasikan Blues lead menunggangi beat oldskool ala Overkill dengan ambang batas atas BPM.
Pengalaman pertama saya mendengar Minatory lewat ReverbNation sekitar tahun 2012-2013.
Saya masih ingat mengunduh "The Struggle for Victory" untuk playlist menyetir dan intens mendengarkan "Rebirth of Achilles" yang menjadi favorit saya; sebuah Metalcore modern yang menjadi soundtrack hidup di awal fase konsekuensi.

Karena itu pada saat Gus Wira menghubungi saya mengajak GEEKSSMILE berpartisipasi dalam launching LP perdana mereka Life Racer saya tidak berpikir panjang, hanya mengecek jadwal personnel yang lain untuk memastikan kesiapan mereka. Saya masih ingat membalas pesannya dengan "OK, let's make a great show Gus!"
Secara tematis, Life Racer menganalogikan hidup sebagai sebuah balapan roda 2 yang mengedepankan kecepatan sebagai faktor utama; sebuah tema yang secara kontras dipinjam dari Seringai; faktanya, album ini adalah contoh Seringai worship paling lugas yang pernah saya dengar.
Sebagai seorang Serigala Militia yang taat, saya bisa dengan akurat menyebutkan referensi riff maupun pola yang digunakan Minatory dalam tiap lagu dalam album ini, tapi tulisan pendek ini bukanlah sebuah ulasan melainkan sebuah apresiasi atas sebuah karya, persahabatan dan perjalanan; karena itu saya akan lebih banyak memberi masukan dengan harapan mereka akan terus berkarya.
Dalam konteks album perdana, Minatory mengeksekusinya dengan sangat baik; mereka melakukan evolusi secara musikal dengan tema yang sesuai dengan output. Tema balapan yang mereka usung sangat solid dan masih bisa dieksploitasi lebih dalam untuk rilisan selanjutnya. Contohnya, mereka bisa mengeksplorasi tema baru; touring yang saat diterjemahkan akan menjadi sebuah rilisan yang berisi satu lagu multi chapter dengan durasi 15-30 menit yang membahas aspek-aspek touring mulai dari nama tour, persiapan, nama motor yang digunakan, situasi dijalanan sampai perjalanan pulang; seperti versi mikro Dopesmoker.
Secara musikalitas, Life Racer sudah sangat keren; Minatory memiliki kemampuan menulis lagu yang sangat baik, ditunjang dengan skill masing-masing personel yang juga diatas rata-rata. Personally saya suka dengan permainan drum dan bass track di album ini; dapur pacu yang sangat solid dengan track bass yang berani. Sang vokalis memiliki karakter yang mudah dikenali dan bisa bernyanyi balada di "Suara yang Nyata", ini nilai plus disamping kemampuannya menggonggong di hampir semua lagu. Formasi gitar ganda masih bisa dimaksimalkan, terutama dalam sektor sound dan peran dalam mengisi bagian lagu. Saya hanya kurang sreg dengan hasil masteringnya saja, tapi lagi-lagi ini selera personal; mungkin saya terlalu banyak mendengar Black Metal.
Lagu sorotan: Melawan Depresi, Suara yang Nyata dan Tanked for You
Semoga tulisan ini memantik rasa penasaranmu mendengar Life Racer.
#MinatoryBali
Prima Yudhistira
12.02.2023
Sekelebat pertanyaan tiba-tiba muncul mana kala halaman demi halaman terbitan berkala Prabhajñāna saya buka. Pertanyaan yang mengusik saya sejak mengenal khazanah teks-teks Bali yang melimpah -- yang bagi saya tak cukup umur untuk mendalami semua khaznah itu. Bagi saya, mempelajarinya sudah seperti menemukan "pelukatan" untuk diri sendiri -- menemukan nutrisi hidup.
Pertanyaannya kemudian, apa sumbangan Ilmu-Ilmu Bali untuk jawaban hari ini dan hari depan Bali ? Pertanyaan ini tentu tak mudah dijawab. Tak mudah dijawab karena hampir sebagian dari kita menanggung bebab akut, diblokir sejumlah kesenjangan -- baik itu kesenjangan aksara dan kesenjangan bahasa.
Kita bisa membayangkan, apa arti terbitan Prabhajñāna di depan generasi yang mengalami dua kesenjangan akut itu? Mereka pasti mengalami keterasingan, mengingat jarak kultural, jarak historis, dan jarak tradisi teks adalah juga beban bagi mereka. Bila kondisi ini tak dijembatani, tentu membuat siapa saja jauh dari akar kebudayaan. Menjadi generasi tanpa identitas, terombang-ambing karena tak memiliki pegangan nilai-nilai. Terhanyut di samudera luas modernitas, dan di situ setiap orang pasti butuh pegangan -- sekecil apapun pegangan itu. Pegangan itu adalah nilai-nilai -- di dalamnya ada keyakinan dan norma-norma. Sama seperti orang terhanyut di samudera lepas, ia butuh semacam pelampung kecil, supaya mereka tak mudah terhanyut atau tenggelam.

Sekiranya kita tak ingin terombang-ambing, tergerus gelombang modernitas dangkal, apakah kemudian semua dari kita harus menjadi ahli sastra, mendalami teks-teks kuna dengan seksama?
Tentu tidaklah demikian strateginya, dan karena di sini, ranah ini kemudian menjadi tanggung jawab sarjana sastra -- ia menjadi timba, menjadi jembatan untuk menghidangkan "masakan lezat" teks-teks sastra guna menjadi nutrisi penguat nilai serta mudah dicerna khalayak pembaca. Ini adalah tugas humaniora yang tak bisa ditunda -- karena ia menjadi semacam penjaga benteng kemanusian kita. Kita boleh menguasai apa saja, mendalami bidang-bidang keilmuan yang beragam dan luas. Namun kita tetap butuh humaniora, jika tidak, kita akan mengalami keterasingan dan de-moralisasi. Jiwa-jiwa kering tanpa nutrisi rohani, robot-robot tanpa perasa.
Sampai di sini, tugas sarjana sastra tak cuma melulu menyajikan teks-teks itu secara akademis -- justru ia bisa menjadi penghidang piawai di tengah-tengah pilihan bacaan yang prural dan beragam. Di tengah-tengah banjir bah kebudayaan nirkabel; medsos, instagram, tiktok, dll. Kita butuh sesuatu yang baru dan segar tanpa kehilangan nilai-nilai. Seperti halnya pujangga Rabindranath Tagore, menghidangkan Gitanjali dengan apik di zamannya, menyajikan teks-teks tua dari kabut mistis Upanisad -- di mana sesungguhnya; Gitanjali atau mungkin juga Tukang Kebun tak cuma karya sastra, tapi Upanisad yang dibahasakan secara baru, menyala dengan bahasa bersinar.
Itulah contoh kongkrit, bagaimana teks-teks kuna itu dinyalakan dengan bahasa yang baru. Spirit dan semangat yang baru. Dan mungkin di situ kita bisa membangun suatu adab yang baru. Inilah salah satu tugas dari sarjana sastra. Tentu di pundaknya ada tugas-tugas yang sama beratnya -- setidaknya ia harus terbebas dari dua kesenjangan akut, yakni: kesenjangan bahasa dan kesenjangan aksara.
Hal paling ditakuti tentu adalah tugas-tugas filologis, karena tugas ini di samping memerlukan kesuntukan dan ketelitian, ia juga memerlukan kecintaan.Punagi dari seorang filolog adalah kecintaannya pada teks. Tanpa pengkajian teks dengan baik, mustahil pranata, sejarah, dan kebudayaan masa silam bisa diselami dengan baik. Mustahil membangun makna-makna baru dari situ. Tak banyak thesis dan disertasi yang menekuni bidang ini secara komperehensif dan boleh jadi ini studi yang paling menantang, menakutkan, sekaligus mengasykkan.
Namun hari ini kita layak berbesar hati, sejumlah sarjana sastra dari Unit Lontar Universitas Udayana dengan energi sedikit bersuntuk , sangat percaya diri menghadirkan hasil kajiannya dalam terbitan berkala bertajuk Prabhajñāna. Setidaknya kajian-kajian ini menunjukkan kita peta-peta kognitif perihal kekayaan khasanah sastra Bali yang amat berlimpah itu.
Dan sebagai peta kebudayaan yang utuh, Bali terang memiliki unicum tersendiri, suatu pandangan kosmos tersendiri pula. Di pulau kecil ini, di samping keunikan alamnya, memiliki empat danau berudara dingin, Bali memiliki tradisi yang unik pula, memiliki bahasa, aksara, dan susastra yang berbeda dengan tradisi Nusantara lainnya, terkecuali dalam garis genetik kultur Hindu Jawa klasik. Bahkan agama dan keyakinan-keyakinannya yang masih hidup pun terbilang amat sangat khusus -- sebagaimana kemudian dinyatakan budayawan anumerta I Gusti Bagus Sugriwa, menyebutnya sebagai "Hindu Bali".
Sebagai orang non akademis, saya berusaha melihat kajian-kajian yang disajikan dalam terbitan Prabhajñāna dengan kaca mata orang awam, dari dua sisi yang saling berkelindan, yakni dari cara hidup yang benar dan cara mati yang benar. Orang-orang terpelajar dalam teks lebih memahaminya sebagai Dharma Kahuripan dan Dharma Kepatian, tugas untuk hidup dan tugas untuk mati.
Jadi dengan amat sederhana, bila kita kelompokkan teks-teks Bali itu, kategorinya cuma ada dua. Pertama, adalah teks-teks yang berkaitan dengan cara hidup yang benar. Kedua, adalah teks-teks yang bertemali dengan cara mati yang benar. Itulah "agama" bagi orang Bali -- agama yang berkaitan dengan proses mengada dan proses meniada. Dua sisi yang biasanya disambut dan dilepas dengan meriah.
Lihatlah upacara manusa yadnya dari lepas awon hingga upacara pernikahan, sungguh dirayakan dengan meriah. Perhatikan juga upacara pitra yadnya, kadang menjadi upacara pelepasan begitu bergemuruh.
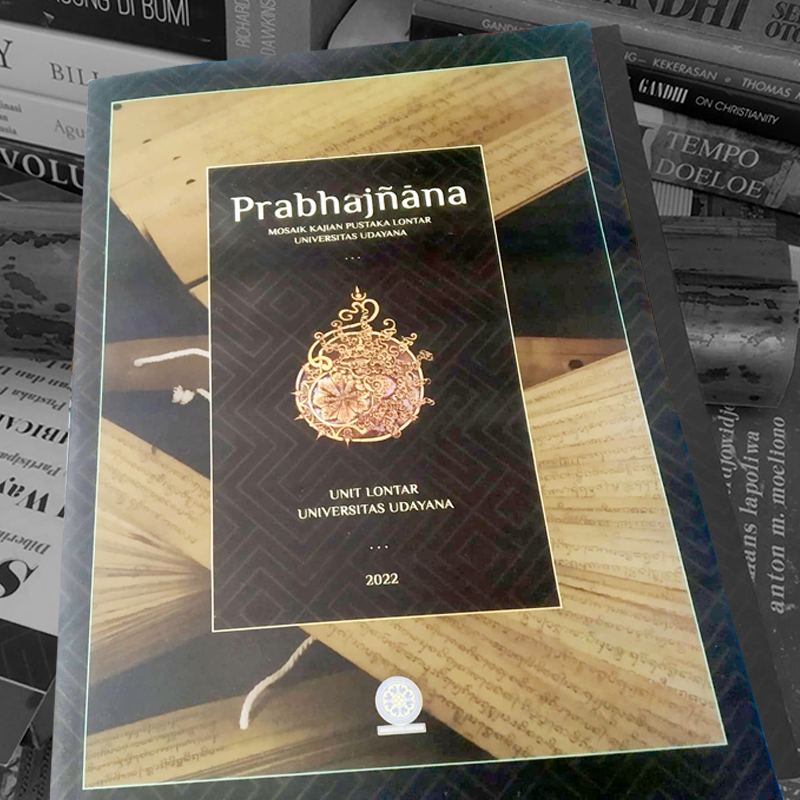
Menyebut beberapa nama, tulisan-tulisan dengan kategori Dharma Kahuripan, dengan lumayan jelas bisa kita simak dari tulisan Dr. I Wayan Suardiana [ Aji Pangintar Pantun: Teks Panduan Bercocok Tanam Padi di Sawah serta Siklus Upacaranya]. Kajian I Wayan Cika & Putu Eka Guna Yasa [ Bentuk Berubah Nilai Etiket Tetap: Transformasi Teks "Kakawin Putra Sasana" dalam "Geguritan Putra Sasana"]. Tulisan Putu Ari Suprapta Pratama [ Bhama Kretih: Pengetahuan Tradisional Tentang Pekarangan]. Tulisan Pande Putu Abadi Jaya [Makna Simbolis dan Suluh Kehidupan dari Peralatan Pandai Besi dalam Khazanah Lontar di Bali], tulisan Sri Jumaidah & Putu Widhi Kurniawan [ Memaknai Lontar Kanda Empat Bhuta: sebagai media Pembelajaran Seorang Ibu]. Tulisan I Made Suastika [Pengobatan Tradisional Bali], tulisan I Putu Eka Guna Yasa [Brata Amrétasnātaka dalam Sarasamuccaya: Dimensi Waktu dalam Seksualitas sebagai Penentu Generasi Berkualitas] dll.
Dalam tulisan I Wayan Suardiana, akhirnya kita tahu, bahwa Bali memiliki banyak teks perihal bagaimana bersawah dan merawat sawah dengan kesantunan-kesantunan agraris. Ini menunjukkan betapa pentingnya devosi "karma kanda" sebagai doa dalam tindakan tentang bagaimana tanah, badan wadag ibu bumi dimuliakan dalam kerja, dirawat, ditanami supaya menghasilkan amreta bagi hidup. Petani yang merawat tanah tanpa keluh dipastikan dianugerahi kesabaran, seperti juga ibu bumi lambang kesabaran itu.
Dan teks-teks yang disebut Wayan Suardiana [ di halaman delapan buku ini], semisal Usadha Sawah, Tingkah Makarya ring Prathiwi, Pratingkahing Wwang Magaga Sawah, Tingkahing Angawe Sawah, dan lain-lainnya bisa dipastikan adalah seperangkap ilmu-ilmu Bali yang ditulis dari pengalaman kerja.Bukan ditulis di atas meja. Dan pengalaman-pengalaman itu menghasilkan tehnik-tehnik mengolah tanah dengan benar,sebagaimana pengalaman orang Bali sendiri. Apa yang kemudian disebut kreta masa dalam bercocok tanam ala Bali misalnya, terang terbaca sebagai salah satu cara mengendalikan hama, di samping hal khusus soal hama yang diterangkan Usadha Sawah.
Tentu masih banyak naskah-naskah yang berkaitan dengan Dharma Kahuripan-- yang layak kita bahas di sini. Misalnya soal Pengobatan Tradisional sebagaimana kajian yang dilakukan Bapak Made Suastika. Ternyata dunia teks Bali menyediakan beragam cara soal bagaimana menangani penyakit -- mulai dari diagnosis sampai pronogsis. Kita juga menemukan teks-teks pengobatan yang bersifat spesialis, sebutlah misalnya soal Usadha Netra, Usadha Edan, Usadha Taru Pramana, Tetenger Wong Beling, Usadha Kecacar, Usadha Cetik, dan sebagainya. Teks-teks ini memerlukan studi yang komperehensif dan harus ditangani secara spesialis juga. Sebagai warisan ilmu pengobatan tradisional, Usadha Bali masih menyediakan lapangan pengkajian yang luas, studi yang sangat menantang -- yang sebagian sudah dikerjakan oleh Dr. Med. Wolfgang Weck. Dengan mempergunakan 256 lontar, mewawancarai 43 narasumber, Weck akhirnya menerbitkan buku yang nyaris menjadi magnum opus dengan judul Hilkunde und Volkstum auf Bali [Pengetahuan tentang Penyembuhan dan Pekerti Rakyat Bali]. Baru kemudian setelah beberapa dekade, buku Usada Bali (1993) karya Prof. Dokter Ngurah Nala terbit. Walau demikian teks-teks Usadha masih memerlukan sentuhan para filolog, guna menemukan, menyibak belantara istilah, serta norma-norma etik yang ada di belakang teks. Sekali lagi ini menjadi tugas sarjana sastra Bali dan Jawa Kuna.
Wilayah teks-teks dalam kategori Dharma Kahuripan sesungguhnya amat luas, di samping tentang ilmu bangunan, Kosala-Kosali, kita juga menemukan perihal teks-teks etik dengan tajuk sasana. Apa yang dibahas I Wayan Cika bersama Putu Eka Guna Yasa perihal transformasi teks Kekawin Putra Sasana dalam Geguritan Putra Sesana menunjukkan pada kita, bahwa Bali memiliki cara-cara mengedukasi secara melekat, di mana pertama-tama tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab orangtua.
Soal bagaimana mengkondisikan generasi berkualitas, orang-orang modern memiliki tahap pendidikan pralahir yang disebut prenatal education, yakni usaha pasangan suami istri "mendidik' janin di dalam kandungan. Namun lebih awal dari "pendidikan janin" dalam kandungan, teks Sarasamuccaya malah mengawali proses itu dari dimensi waktu, kapan hari yang tepat dan dibolehkan berhubungan seks -- sebagaima bahasan menarik yang diasajikan Putu Eka Guna Yasa berdasarkan brata amrétasnātaka. Ini adalah hal sangat penting dibahas dalam sejumlah lontar seksologi Bali. Sebutlah misalnya lontar Smarakrida Laksana, Pameda Smara, Cumbana Sasana, dan lain sebagainya, menjabarkan etiket ini secara panjang lebar.
Sesungguhnya teks-teks dalam kategori Dharma Kahuripan dibetangkan layaknya kurikulum, menuju jalan meniada dengan cara yang benar -- suatu kepulangan di mana sang jiwa mereguk santapan sangupati, bekal kepulangan yang disebut amrétajiwa. Suatu bahasan menarik perihal topik ini disajikan Ida Bagus Anom Wisnu Pujana. Teks Swacandha Mārana yang dibahas penulis memang membentangkan jalan, pertanda, dan kemenangan atas kematian. Dikatakan oleh penulis, seorang yogi yang mengetahui dan menerapkan marga tiga saat menjelang kematiannya, ia dapat memilih nadi mana yang dijadikan jalan atma untuk berpulang, lepas dari badan wadahnya. Apabila anawaha sebagai jalan, atma akan menuju alam dewata. Jika rasawaha sebagai jalan, maka atma akan menuju alam pitra. Dan jika pranawaha sebagai jalan, maka sang yogi akan mencapai moksa.
Sebenarnya ada dua teks yang boleh kita dudukan sebagai teks dalam kategori risalah mistis Dharma Kepatian dalam buku ini. Selain Swacandha Mārana ada teks Dharma Sunya yang didekati dengan cara pandang filsafat stoik oleh Ni Made Ari Dwijayanti. Suatu bahasan menarik tentang bagaimana cara pandang Yunani itu membingkai, memformulasikan teks-teks kelepasan ala Bali. Namun di sisi lain pasti ada persinggungan-persingungan kategoris, bagaimana mensepadankan dunia Bali dan dunia Atena soal kematian yang benar. Pertanyaan kemudian, apakah akar dan motif dua dunia itu memang sama? Untuk lebih jelasnya, silakan baca tulisan Ni Made Ari Dwijayanti.
Sampai di sini, kita boleh meraba jawaban dari pertanyaan, apa sumbangan ilmu-ilmu Bali untuk hari ini dan hari depan? Lamat-lamat saya seperti mendengar cibiran. Kita adalah orang "kaya" yang keburu merasa miskin. Padahal kita memiliki kotak warisan di mana jawaban-jawaban itu tertulis. Mempelajarinya, mengalaminya, lalu membadankannya bisa jadi membuat setiap orang selalu rindu kembali, lalu pulang membawa bekal amretajiwa. Pihala bagi yang jaya atas kematian, mrityunjaya.
I Wayan Westa
Pakubuan Kusa Agra
Sugian Jawa, 29 Desember 2022
Note:
Materi ini disajikan dalam acara Peluncuran dan Diskusi Buku Prabhajñana: Mosaik Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana, tanggal 29 Desember 2022.
Tertanda:
Tim Unit Lontar Universitas Udayana.